| Menguak Misteri Vinaya |
| oleh: Jan Sanjivaputta |
Tak perlu diragukan, hampir semua umat Buddha pasti telah mengetahui bahwa Vinaya adalah peraturan-peraturan kedisiplinan yang telah digariskan oleh Sang Buddha Gotama kepada umat-Nya —terutama para bhikkhu. Meskipun demikian, rasanya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa banyak di antara mereka yang ternyata kurang mengerti mengapa Vinaya itu harus digariskan? Apa sesungguhnya dasar dan fungsi utamanya? Dan apakah manfaat yang dapat diraih dengan menaatinya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini kiranya dapat ditemukan dalam uraian artikel di bawah ini. Lebih daripada itu, artikel ini kiranya dapat menunjukkan alternatif yang tepat bagi umat Buddha pada masa sekarang ini, yang sedang dalam "kebimbangan" untuk memutuskan diri —antara memihak usaha-usaha pengurangan, pengubahan dan penyelewengan Vinaya ataukah sebaliknya menunjang usaha-usaha pelestarian, pemeliharaan dan pemertahanannya.
Sudah semestinya bila setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Sang Buddha selalu berusaha benar-benar berkiprah kepada Kitab Suci Tipitaka (Pali) karena Tipitaka itulah satu-satunya kitab suci yang dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kemurniannya. Hal-hal yang berhubungan dengan mistik, klenik, ketahyulan, mitos, legenda maupun dongeng tidak mampu mencemarinya. Penyebabnya tiada lain adalah bahwa penulisannya dipercayakan kepada orang-orang suci yang sangat kompeten dalam mengingat, menghafal dan menembus Ajaran-ajaran murni Sang Buddha Gotama. Kitab Suci Tipitaka ditulis tidak berdasarkan pada pengertian, pandangan pribadi penulisnya maupun bisikan-bisikan gaib yang kebenarannya masih meragukan. Pada waktu menulisnya —juga sebelum dan sesudahnya— mereka betul-betul dalam keadaan sadar penuh (satisampajanna) sehingga tidak ada satu roh halus pun turut campur tangan dengan merasuki batinnya. Sebagai akibatnya, terwujudlah suatu Kitab Suci Tunggal yang benar-benar tiada duanya. Tidak ada Tipitaka versi Bhikkhu M, Tipitaka versi Bhikkhu L dan Tipitaka versi Bhikkhu Y; yang isinya tidak saling menunjukkan kesamaan yang utuh. Satu keistimewaan lain terletak pada segi kebakuannya. Sudah menjadi catatan sejarah bahwa sejak pertama kali ditulis hingga saat ini, Kitab Suci Tipitaka tidak pernah mengalami perubahan, perbaikan maupun pembaharuan.
Hampir semua aspek kehidupan dijelaskan dan diterangkan dalam Kitab Suci Tipitaka. Tidak sedikit cabang ilmu pengetahuan yang pada dasarnya dikembangkan dari pengertian-pengertian yang terdapat dalam Kitab Suci Tipitaka. Tampaknya "keampuhan" Kitab Suci Tipitaka juga telah tercium oleh seorang fisikawan berdarah Yahudi yang rumusannya tentang Teori Relativitas Umum pernah menggemparkan dunia ilmu pengetahuan, Albert Einstein. Tanpa merasa malu dan tanpa mengurangi penghargaannya pada ilmu pengetahuan modern, Albert Einstein menyatakan, "Apabila ada suatu agama bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ilmu pengetahuan modern, maka agama itu tentunya adalah agama Buddha".
Secara garis besarnya, Kitab Suci Tipitaka dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama disebut Vinaya Pitaka. Kitab ini berisikan peraturan-peraturan kedisiplinan[1]. Kelompok kedua disebut Sutta Pitaka. Kitab ini merupakan kumpulan khotbah-khotbah Sang Buddha. Kelompok terakhir disebut Abhidhamma Pitaka. Tidak seperti dua kitab pertama yang ditulis dengan gaya bahasa naratif dan sederhana, kitab yang berisikan ajaran-ajaran mendalam tentang filsafat Buddha Dhamma ini ditulis secara lebih sistematis, bersifat teknis dan analitis.
| [1] | Jumlah peraturan kedisplinan yang termaktub dalam Vinaya Pitaka itu lebih dari 227. Dua ratus dua puluh tujuh hanyalah peraturan kedisplinan yang tertulis dalam Patimokkha Sila yang lazimnya dibacakan oleh para bhikkhu setiap empat belas hari sekali. Oleh karena itu, rasanya kurang jujur bila dinyatakan bahwa peraturan-peraturan kedisplinan yang dilatih dan dilaksanakan oleh para bhikkhu Theravada lebih sedikit daripada yang dilatih dan dilaksanakan oleh bhikkhu Mahayana —sekalipun mereka memiliki Bodhisattva Sila karena peraturan-peraturan kedisiplinan itu —kecuali Vegetarisme dan lain-lain— sesungguhnya telah ada di dalam Vinaya Pitaka dan beberapa sutta. |
Vinaya Pitaka merupakan bagian penting dalam menentukan perkembangan agama Buddha. Dinyatakan bahwa biarpun Sutta-sutta dan Abhidhamma sudah dilupakan untuk selama-lamanya, agama Buddha tetap dapat dipertahankan selama Vinaya tidak dimusnahkan. Dalam hal ini, Vinaya Pitaka —lebih tepatnya, mâtikâ dari Ubhatovibhanga— rupanya berperan sebagai benteng terakhir dalam mempertahankan eksistensi agama Buddha.
Mengingat sedemikian penting peranan peraturan-peraturan kedisiplinan, agaknya cukup beralasan bila para bhikkhu yang menghadiri Pasamuan Agung Pertama memutuskan untuk membacakan Vinaya lebih dulu alih-alih Dhamma. Pada kesempatan itu Bhikkhu Upâli-lah yang diberi kehormatan untuk membacakannya. Penentuan ini diputuskan bukan karena Bhikkhu Ananda tidak kompoten dalam hal ini, tetapi semata-mata bertitik tolak dari pernyataan Sang Buddha —ketika masih hidup— bahwa antara para bhikkhu siswa-siswanya, Bhikkhu Upâli-lah yang paling utama dalam mengingat peraturan-peraturan kedisiplinan[2].
| [2] | Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, lihat The Inception of Discipline and Vinaya Nidâna. |
Sudah menjadi tata cara yang baku bahwa sebelum berhadapan dengan teori dan praktek yang rumit tentang Pengembangan Batin (Samâdhi) dan Kebijaksanaan (Pañña), seorang musafir dalam Dhamma sedikit banyak harus berkenalan terlebih dahulu dengan Sila atau peraturan-peraturan kedisiplinan yang pada umumnya termaktub dalam Vinaya Pitaka. Sila —yang terwujud dalam tiga faktor dari Jalan Mulia Berfaktor Delapan— merupakan tahapan pertama yang harus dilatih dan dikembangkan oleh seorang pencari Kebahagiaan Sejati. Tanpa melaksanakan peraturan-peraturan kedisiplinan, tidaklah mungkin seseorang dapat memiliki Samâdhi. Dengan tidak adanya Samâdhi, mustahil Pañña akan muncul dan berkembang. Pelaksanaan peraturan-peraturan kedisiplinan adalah syarat mutlak pertama yang tidak dapat ditawar-tawar. Beserta Samâdhi dan Pañña, melaksanakan peraturan kedisiplinan telah diabsahkan sebagai Sarana Tunggal menuju kesucian dan kebebasan sejati.
Walaupun dinyatakan sebagai landasan dari Jalan Mulia Berfaktor Delapan, pelaksanaan peraturan-peraturan kedisiplinan bukan berarti harus dijalankan secara terpisah dari lima faktor lain dalam Jalan Mulia Berfaktor Delapan. Jalan Mulia Berfaktor Delapan haruslah dilaksanakan dan dikembangkan selangkah demi selangkah dalam satu kesatuan dan kebersamaan. Kedelapan faktornya saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan perkataan lain dapatlah dinyatakan bahwa, "Tidak ada pelaksanaan peraturan-peraturan kedisiplinan dan Pañña; tidak ada Pañña tanpa pelaksanaan peraturan-peraturan kedisiplinan dan Samâdhi". Di sinilah terlihat keunikan Jalan Mulia Berfaktor Delapan.
Dalam kaitannya dengan si pelaksana, peraturan-peraturan kedisiplinan sebenarnya tidak bisa dikatakan bersifat pasif. Fungsi peraturan-peraturan kedisiplinan yang utama memang ditujukan untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan jahat, tetapi pada sisi lain, pelaksanaan peraturan-peraturan kedisiplinan juga diakui sebagai suatu cara untuk berbuat bajik —termasuk salah satu dari sepuluh perbuatan bajik (Dasapuññakiriyavatthu). Dengan demikian, peraturan-peraturan kedisiplinan sesungguhnya dapat dikatakan berfungsi ganda (rangkap). Atas dasar ini, pelaksanaan peraturan-peraturan kedisiplinan pasti akan memberikan hasil/manfaat ganda juga. Bagaimana suatu pelaksanaan peraturan-peraturan kedisiplinan memberikan hasil/manfaat memang tidak bisa dibuktikan secara nyata melalui pengujian di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Namun, hal itu bukan suatu perintang bagi seseorang untuk mempercayainya. Logika umum telah mengakui hal itu sebagai kebenaran mutlak. Hasil/manfaat dari pelaksanaan peraturan-peraturan kedisiplinan bukan suatu teka-teki yang tak terjawab! Pembuktian secara nyata memerlukan proses yang lebih rumit, yaitu melalui pelaksanaan oleh diri sendiri; penelitian, perenungan dan penembusan dalam batin sendiri. Pembuktian melalui orang lain hanya mampu memberikan gambaran abstrak.
Satu hal yang perlu diketahui ialah bahwa dalam pembuktian secara nyata itu juga akan terlihat keunikan lain dari Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha Gotama. Suatu perbuatan dapat memberikan hasil/manfaat nyata tanpa campur tangan pihak kedua —yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Hal inilah yang membuat umat Buddha tidak perlu mengorbankan harga dirinya di depan makhluk-makhluk lain apapun juga. Kemandirian telah menjadi satu bagian penting yang tak terpisahkan dari kehidupannya, sehingga pantas dan selayaknyalah bila umat Buddha disebut sebagai makhluk berjiwa besar yang benar-benar merdeka.
Berbicara tentang fungsi, manfaat dan seluk beluk peraturan kedisiplinan, rasanya sulit bagi seseorang untuk menghindari pembicaraan tentang sejarah peraturan kedisiplinan itu sendiri.
Beberapa waktu setelah Sang Buddha mengkat (mencapai Parinibbana), peraturan-peraturan kedisiplinan telah berkali-kali menghadapi prarongrongan dari beberapa orang yang berusaha memudarkan kemurnian dan keasliannya. Apabila usaha jahat itu dilancarkan oleh orang-orang yang sama sekali tidak berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, hal itu kiranya bisa dianggap sebagai kejadian yang lumrah. Tetapi sayangnya, ternyata justru orang-orang dalamlah yang melakukannya.
Bermacam-macam dalih mereka kemukakan hanya untuk memperkuat alasan mereka dalam upaya mengurangi, mengubah dan meniadakan beberapa peraturan kedisiplinan. Di antara semua dalih itu, ada beberapa dalih yang agaknya cukup perlu dikaji dan ditinjau lebih lanjut. Dengan penuh rasa percaya pada swatafsir, mereka menyatakan bahwa berdasarkan pada apa yang disampaikan kepada Bhikkhu Ananda menjelang parinibbana-Nya, Sang Buddha telah memberikan izin kepada Sangha untuk meniadakan —bila Sangha menghendaki— beberapa peraturan kedisplinan kecil dan kurang penting[3]; maka pengurangan, pengubahan dan peniadaan peraturan-peraturan kedisiplinan kecil dan kurang penting adalah suatu "perintah tidak langsung" dari Sang Buddha sebagai pesan terakhir yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan.
| [3] | Menurut Bhikkhu Nagasena, yang dikategorikan sebagai peraturan-peraturan kedisiplinan kecil adalah "dukkata" atau "tingkah laku salah", sedangkan peraturan-peraturan kedisiplinan yang kurang penting adalah "dubbhasita" atau "ucapan salah". Oleh karena itu, bila Vajjiputtaka mengusulkan peniadaan 10 vinaya kecil (dasavatthuni) dengan menyisipkan beberapa peraturan kedisiplinan yang berkategorikan sebagai "pacittiya", agaknya itu dapat dianggap sebagai usul yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan. |
Dalih itu dikemukakan secara resmi oleh Vajjiputtaka —sekelompok besar bhikkhu dari suku Vajjian[4]— kira-kira seratus tahun sesudah Sang Buddha mencapai Parinibbana. Para bhikkhu yang menghadiri Pasamuan Agung Kedua —yang diselenggarakan di Vesali— tidak dapat menerima dalih tersebut. Mereka tetap mempertahankan keteguhannya untuk memelihara kemurnian peraturan-peraturan kedisiplinan sebagaimana diteladankan oleh para bhikkhu yang menghadiri Pasamuan Agung Pertama yang dipimpin oleh Bhikkhu Mahâkassapa. Mereka sepakat untuk tidak mengurangi, mengubah maupun meniadakan peraturan-peraturan kedisiplinan yang telah ditetapkan, dengan alasan bahwa hal itu akan memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan agama Buddha karena secara langsung maupun tidak langsung hal itu akan menurunkan keyakinan umat.
| [4] | Buddhaghosa mempunyai anggapan bahwa kaum heretik ini termasuk komplotan yang sama dengan para bhikkhu yang memisahkan diri dari Sangha dan menggabungkan diri dengan Devadatta. |
Sehubungan dengan izin yang ditawarkan oleh-Nya kepada bhikkhu Sangha untuk meniadakan beberapa peraturan kedisiplinan kecil dan kurang penting, Bhikkhu Nagasena memberikan suatu wawasan yang luas dan logis. Beliau menyatakan sebagaimana seorang Raja Pemutar Roda Pemerintahan yang mungkin berpesan kepada putranya —sebagai ahli waris tahta kerajaan—, "Putraku tersayang, seperti yang kita ketahui, Negara Besar ini dibatasi oleh lautan pada setiap sisinya, namun sulit untuk dirawat dan dijaga lebih lama dengan kekuasaan. Oleh karena itu, Putraku tersayang, lepaskanlah semua daerah yang jauh setelah aku tiada". Demikian juga halnya dengan yang dilakukan oleh Sang Buddha. Beliau bersikap demikian itu untuk "menguji" para bhikkhu apakah setelah kemangkatan-Nya para bhikkhu akan mentaati peraturan-peraturan kedisiplinan yang kecil dan kurang penting ataukah mereka akan melanggar, mengabaikan atau bahkan menolaknya.
Sebagai putra mahkota yang telah mewarisi kerajaan ayahandanya, anak raja tersebut tentunya tidak akan begitu saja melepaskan daerah kekuasaannya yang sulit dijangkau. Bahkan apabila keadaan memungkinkan, ia akan berusaha untuk memperluas daerah kekuasaannya. Melindungi, menjaga dan merawat setiap jengkal tanah yang termasuk dalam daerah kekuasaannya sesungguhnya merupakan kewajiban seorang Raja Pemutar Roda Pemerintahan. Seorang raja yang penuh rasa tanggung jawab akan mempertahankan setiap jengkal tanah kekuasaannya dari rongrongan musuh —baik dari dalam maupun dari luar— walaupun untuk memenuhi tugas itu ia kadang-kadang dituntut untuk mengorbankan segala-galanya —termasuk jiwanya.
Demikian juga yang seharusnya diperbuat oleh para bhikkhu. Karena telah diwarisi kekayaan Dhamma dan Vinaya oleh Sang Buddha, para bhikkhu —dan umat Buddha lainnya— yang mempunyai rasa tanggung jawab dan mengetahui kewajiban tentunya akan berusaha sedapat-dapatnya untuk memelihara, merawat dan menjaga Dhamma dan Vinaya.
Perihal "pengujian" ini memang tidak diungkapkan secara resmi dalam Kitab Suci Tipitaka, namun itu bukan berarti bahwa pernyataan Bhikkhu Nagasena tidak bernapaskan Ajaran Sang Buddha. Pitutur Sang Buddha Gotama kepada para bhikkhu yang tinggal di sekitar Râjagaha tampaknya dapat dijadikan bukti untuk menunjang dan menguatkan pendapat Bhikkhu Nagasena. Pada kesempatan itu Sang Buddha menegaskan bahwa kesejahteraan dan kemajuan para bhikkhu dapat diharapkan selama para bhikkhu tidak menghapus peraturan-peraturan kedisiplinan yang sudah ada, atau dengan kata lain "tetap mentaati peraturan-peraturan kedisiplinan yang telah ditetapkan". Berdasarkan sabda suci itu, dapatlah disimpulkan bahwa prasangka bhikkhu-bhikkhu suku Vajjian, yang menganggap Sang Buddha memberikan "perintah secara tidak langsung" untuk mengurangi, mengubah dan meniadakan peraturan-peraturan kedisiplinan kecil dan kurang penting lebih mendekati (atau bahkan memang berada di) kutub ketidakbenaran.
Sebenarnya, pengurangan, pengubahan atau peniadaan peraturan-peraturan kedisiplinan dapat dianggap sebagai suatu usaha yang menunjukkan rasa tidak menghargai dan tidak menghormati Sang Buddha; atau dengan kalimat yang lebih tandas, suatu usaha untuk mengangkangi kebijaksanaan Sang Buddha.
Bagaimanapun kecil dan kurang pentingnya suatu peraturan kedisiplinan, itu semua diberlakukan oleh Sang Buddha dengan dasar-dasar dan alasan yang kuat. Peraturan-peraturan kedisiplinan ditetapkan bukan tanpa dilandasi oleh Kewaskitaan, Kebijaksanaan dan Kesempurnaan. Hal inilah yang membuat seseorang berani menyatakan bahwa meskipun seandainya agama Buddha hanya mengajarkan peraturan-peraturan kedisiplinan —tanpa Ajaran tentang Samâdhi dan Pañña— hal itu sudah cukup untuk membuat agama Buddha dihargai sebagai agama besar yang memberikan andil bagi terciptanya perdamaian dunia. Apabila Ajaran Sang Buddha hadir dan menampakkan diri secara keseluruhan —Sila, Samâdhi dan Pañña—, maka agama Buddha layak dan tidak berlebih-lebih bila dinyatakan sebagai agama dari agama-agama!
Tidak perlu disangsikan bahwa ketekunan dan ketaatan para bhikkhu dalam melaksanakan peraturan-peraturan kedisiplinan dapat memperlancar perjalanan mereka menuju Kesucian dan Kebebasan Sejati. Selain itu, mereka juga akan menjadi pantas dan berharga untuk menyandang gelar sebagai pemelihara citra hidup kebhikkhuan sebagaimana diajarkan oleh Sang Buddha. Bahkan, efek positif dari sifat mulia itu tidak hanya berakhir sampai di situ. Di kalangan umat beragama, mereka akan dikenal sebagai bhikkhu-bhikkhu yang mempunyai kharisma cukup besar karena bagaimanapun juga setiap pendiri agama selalu berusaha —terlepas dari persoalan berhasil atau gagal— meletakkan tatanan moral di tempat yang bernilai tinggi.
Sementara itu, para bhikkhu yang miskin rasa tanggung jawabnya dalam melatih dan melaksanakan peraturan-peraturan dan kedisiplinan secara langsung maupun tidak langsung akan menemui hambatan dalam perjalanan menuju Kesucian dan Kebenaran Sejati. Eksistensi bhikkhu-bhikkhu semacam itu juga akan menjadi hambar. Boleh dikatakan bahwa mereka itu tidak memberikan arti penting bagi perkembangan dan kemajuan agama Buddha. Dalam segi sosial, mereka dapat dianggap tidak ikut berperan dalam memelihara Keagungan dan Kebesaran agama Buddha di mata masyarakat umum, dan tanpa disadari hal itu kadang-kadang memberikan peluang pada sementara orang untuk menganggap mereka sebagai bhikkhu-bhikkhu yang dursila.
Jika ada anggapan bahwa peraturan-peraturan kedisiplinan itu membuat seseorang menjadi "terikat", maka jelaslah bahwa anggapan itu merupakan suatu kekeliruan besar yang timbul karena kurangnya pengertian benar akan tujuan pelaksanaan peraturan-peraturan kedisiplinan. Bila ditilik dari tujuan sesungguhnya, pelaksanaan peraturan-peraturan kedisiplinan justru berguna untuk membebaskan seseorang dari "keterikatan"; keterikatan pada safsu-nafsu keinginan yang pasti membuahkan penderitaan. Memang, bagi mereka yang masih dalam taraf latihan, pelaksanaan peraturan-peraturan kedisiplinan kadangkala terasa berat, mengikat, membosankan dan menjemukan; tetapi, bagi seseorang yang sudah dalam taraf yang lebih tinggi, pelaksanaan peraturan-peraturan kedisiplinan akan menjadi suatu kebiasaan positif yang membuahkan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan.
Sebagaimana tertulis dalam The Inception of Discipline and Vinaya Nidâya, Kebijaksanaan yang diputuskan dalam Pasamuan Agung Kedua itu akhirnya mempertajam kesenjangan antara para bhikkhu yang dapat menghargai dan menjunjung tinggi Dhamma dan Vinaya dengan para bhikkhu yang sebaliknya. Memang, hal ini patut disayangkan. Tetapi, itulah kenyataan yang tidak dapat dielakkan. Agaknya sudah menjadi hukum alam bahwa orang-orang yang senang pada keremangan selalu merasa sulit untuk menyesuaikan dan menggabungkan diri dengan orang-orang yang senang pada kecerahan. Para bhikkhu yang merasa keberatan dengan keputusan itu akhirnya memisahkan diri dari kelompok bhikkhu yang tetap memelihara kemurnian dan keaslian Dhamma dan Vinaya. Mereka kemudian mengadakan konsili tersendiri dan menamakan diri Mahasanghika[5].
| [5] | Bhikkhu-bhikkhu golongan ini menolak Ajaran-ajaran yang tertulis dalam Kitab Suci Tipitaka (Pali); di antaranya adalah Parivâra, enam bagian Abhidhamma, Patisambhidamagga, Niddesa dan beberapa Jâtaka. |
Demikianlah sedikit catatan sejarah yang mengisahkan kemelut yang mengawali terjadinya perpecahan dalam tubuh Sangha kira-kira satu abad setelah Sang Buddha Gotama mencapai Parinibbana. Bagi umat Buddha yang hidup pada zaman sekarang ini, peristiwa bersejarah itu sudah semestinya dijadikan bahan pelajaran dan pertimbangan untuk menentukan sikap yang sebaik-baiknya dalam menghadapi masalah Vinaya sehingga peristiwa itu tidak akan terulang lagi pada masa-masa sekarang dan pada masa-masa mendatang.
Sekarang, rasanya tiada sesuatu yang lebih tepat bagi seorang umat Buddha selain mengharapkan agar mereka yang selama ini telah mencampakkan beberapa peraturan kedisiplinan dapat menyadari kekeliruan mereka sehingga tidak lama lagi mereka akan berusaha menemukan, mengumpulkan dan menyatukannya kembali. Apabila harapan luhur itu dapat terwujud, betapa lebih menakjubkan Keagungan dan Kebesaran agama Buddha! Tetapi, mungkinkah hal itu akan menjadi kenyataan? Tidakkah hal itu hanya merupakan suatu lamunan belaka? Entahlah!***
Sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan ini, Vinaya adalah permata berharga yang telah diwariskan oleh Sang Buddha Gotama. Karena itu, sangatlah patut jika kelestarian dan kemurniannya tetap dipertahankan untuk selama-lamanya.
| Sumber: |
| Untaian Dhammakatha (Kumpulan Tulisan), Jan Sanjivaputta, Yayasan Pancaran Dharma, Jakarta, 1987. |
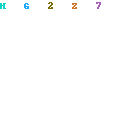
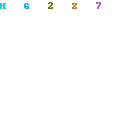
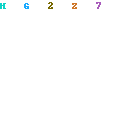
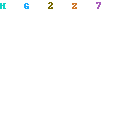
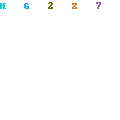
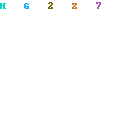
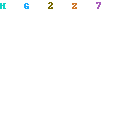
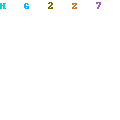
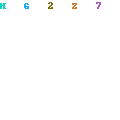




Tidak ada komentar:
Posting Komentar