Terbentuknya Post-Theravãda Sangha Bhikkhuni Dalam Dasa Warsa Terakhir Antara Dilema dan Assumsi Pelecehan Konstitusional Religius Historis
(dengan referensi khusus Pali Tipitaka edisi PTS, London)
Oleh : W. Indasilo*
Sejarah perkembangan agama Buddha mencatat bahwa Sang Buddha dengan tidak secara gegabah menerima dan memberi upasampada kepada kaum wanita untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa Buddhis (Bhikkhuni). 1 Cara yang ditempuh oleh Sang Buddha seperti itu bukan berarti Beliau mendiskriminasi antara kedudukan kaum wanita dan kaum pria, tetapi Beliau dengan pandangan yang bijaksana melihat latar belakang, kondisi dan situasi sosial budaya di India pada waktu itu, selain Beliau tahu bahwa kondisi fisik wanita berbeda dibanding kaum pria. Pada waktu itu, masyarakat di India menganggap bahwa wanita mempunyai derajat yang lebih rendah daripada kaum pria, baik di bidang keagamaan, sosial maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Sebagai contoh dalam kitab Satapatha Brahmana milik agama Brahmanisme menyebutkan bahwa kaum wanita secara ritual keagamaan adalah tidak suci atau tidak bersih (ceremonially is impure). 2 Oleh sebab itu, Sang Buddha yang selalu menghormati dan bertoleransi terhadap tradisi dan kehidupan masyarakat di tempat Beliau hidup dan tinggal, Beliau dengan hati-hati menerima wanita untuk menjalani kehidupan sebagai pertapa Buddhis, meskipun pada waktu itu Jaina Mahavira telah menerima wanita sebagai Jaina "Bhikkhuni". 3 Tetapi, seperti yang diuraikan dalam Cullavagga Pãli, dengan hasutan yang bertubi-tubi dari Bhante Ananda, siswa terdekat Beliau, dan Ibu Mahapajapati Gotami, bibi yang juga ibu tiri Beliau ketika masih menjadi seorang pangeran, Beliau akhirnya mengabulkan kaum wanita untuk mendapatkan upasampada dengan syarat mereka mampu melaksanakan Atthagarudhamma (delapan peraturan penting). 4 Tentu saja dengan penuh antusias Ibu Pajapati dan para ibu lainnya menerima delapan peraturan tersebut, karena memang mereka telah mempunyai motivasi, tekad dan semangat yang sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan sebagai pertapa. 5 Sejak saat itu, terbentuklah Sangha Bhikkhuni untuk pertama kalinya dalam kehidupan Sang Buddha Sakyamuni.
Sejarah kemudian membuktikan bahwa meskipun mereka adalah kaum wanita, tetapi dalam kehidupan spiritual ternyata tidak ada bedanya dengan kaum pria. Mereka justru lebih unggul daripada kaum pria yang masih terbelenggu oleh keserakahan, kebencian dan kebodohan. Dari syair-syair yang terdapat dalam Theri Gatha dan beberapa syair dalam Apadana, kita bisa mengetahui "puisi dan lagu" kemenangan mereka setelah mereka terbebas dari semua kekotoran batin yang menyebabkan setiap insan memutari roda tumimbal lahir tanpa henti ini. Dari dua kitab ini kita bisa mengetahui bahwasanya pencapaian tingkat kesucian ternyata terlepas dari batasan kasta, jenis kelamin dan batasan-batasan lainnya yang dibuat oleh manusia karena keserakahan, kebencian dan kebodohan mereka.
Beberapa abad kemudian, sejarah agama Buddha di Sri Lanka menggoreskan tinta emas dengan mengatakan bahwa sekitar abad ke tiga sebelum masehi, Bhikkhuni Sanghamitta yang tentunya disertai paling tidak empat bhikkhuni lainnya datang ke Sri Lanka untuk membentuk Bhikkhuni Sangha di negara tersebut. 6 Dengan datangnya para bhikkhuni yang disertai tujuan mulia tersebut, dikatakan bahwa banyak kaum wanita yang tertarik untuk menjadi bhikkhuni, dan akhirnya terbentuklah bhikkhuni sangha di Sri Lanka sesuai dengan Vinaya Pitaka yang diajarkan oleh Sang Buddha. 7 Hanya sayangnya, seperti yang diungkapkan oleh Prof. G. P. Malasekara, sejarah kemudian juga mencatat bahwa bhikkhuni sangha yang berkembang dengan baik di negeri Sri Lanka harus mengalami keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan kelanjutannya atau regenerasi. Hal ini berkenaan dengan invasi dan administrasi Pemerintahan Kerajaan Chola dari India Selatan di Sri Lanka sekitar abad X masehi. 8 Sehingga sejak saat itu, sangha bhikkhuni di Sri Lanka mulai sirna dari keberadaannya. Dengan kata lain, tradisi bhikkhuni Theravada yang bermula sejak jaman Sang Buddha tersebut telah terputus. Hal ini dapat diibaratkan empat pelari estafet yang tidak mungkin mencapai finish karena salah satu di antaranya cedera dan meninggal di tengah lapangan sebelum sempat menyerahkan tongkatnya kepada peserta satu team lainnya. Peserta dalam satu team lainnya, bagaimanapun tangguh dan hebat semangatnya untuk menjadi juara, tentunya tidak lagi dapat melanjutkan pertandingan karena dia tidak sempat mendapatkan tongkat dari pelari sebelumnya. Kalaupun kemudian dia mengambil tongkat dari teman yang telah meninggal tersebut, usaha untuk menjadi juara paling tidak sudah 49,9% sia-sia. Hal ini disebabkan karena para peserta lain yang benar-benar fit telah mencapai garis finish terlebih dahulu.
Tetapi dalam satu dasa warsa ini, ada para rohaniawan agama Buddha khususnya dari Sri Lanka, dengan berembel-embel "Theravadin Monks atau Bhikkhu Theravada" di dadanya, yang tentu saja disertai oleh segelintir umat awam, mempunyai ide untuk menghidupkan kembali sangha bhikkhuni Theravada yang telah lama sirna di dunia ini. Padahal sesuai dengan Vinaya Pitaka dalam tradisi Theravada, hal ini sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Kemudian dari ide tersebut, mereka melakukan upasampada dengan embel-embel upasampada 'Bhikkhuni Theravada' di Bodh Gaya. Kelompok lainnya menyelenggarakan di Sarnath di India dengan bantuan para Bhiksuni Mahayana. Setelah itu, terbentuklah Sangha (dengan embel-embel) Sangha Theravada Bhikkhuni di akhir dasa warsa ini, yang kebanyakan mereka adalah dari Sri Lanka.
Terbentuknya Sangha (dengan embel-embel) Bhikkhuni Theravada tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan Sangha dan umat Buddha di Sri Lanka. Tetapi yang jelas banyak pihak yang tidak setuju dengan terbentuknya organisasi baru tersebut. Pemerintah Sri Lanka yang jelas-jelas merupakan salah satu penjaga tradisi Theravada, tidak mengakui keberadaannya sebagai organisasi yang absah. Di pihak sangha, Amapura Nikaya, Ramañña Nikaya, Siam Nikaya Asgiriya Chapter dan Siam Nikaya Malvatha Chapter dengan tegas menolak keberadaan "sangha" baru tersebut. Baru-baru ini Siam Nikaya Kotte Chapter juga menolak. Bahkan Pemimpin Spiritual dan Keagamaan terkemuka Tibet, YM Dalai Lama, yang dikatakan mengikuti secara ketat Vinaya Tradisi Dharmagupta ini, juga tidak menyetujui terbentuknya organisasi baru yang menamakankan diri Sangha Theravada Bhikkhuni. 9 Mereka menolak dengan beralasan bahwa sesuai dengan Vinaya tradisi Theravada, untuk memberikan upasampada seorang bhikkhuni diperlukan dua sangha; bhikkhu sangha dan bhikkhuni sangha. 10 Menurut tata cara yang sesuai dengan vinaya tradisi Theravada, sang calon bhikkhuni untuk pertama kalinya mendapat upasampada dari sangha Bhikkhuni dengan cara melakukan ñatticatutthakammavaca. Setelah itu, dia dihadapkan bhikkhu sangha untuk diupasampada lagi dengan cara ñatticatutthakammavaca, seperti yang dilakukan oleh sangha bhikkhuni. 11 Makanya upasampada ini disebut sebagai "Upasampada dengan dua-empat deklarasi yaitu, satu deklarasi dari sangha bhikkhuni dan lainnya dari bhikkhu sangha" (Atthavacika-upasampada) 12 Mengingat bahwa bhikkhuni sangha Theravada sudah tidak ada lagi, lalu bagaimana mungkin bhikkhu sangha Theravada yang ada, "mencetak" seorang wanita untuk menjadi seorang bhikkhuni Theravada?
Tetapi di samping itu, ada beberapa "bhikkhu" dan umat awam yang menyetujui dan justru merestui sangha baru tersebut. Namun, mereka tidak mewakili nama sangha dan hanya sekedar pandangan personil mereka saja. Mereka berpendapat bahwa Bhiksuni Sangha Mahayana yang ada di China, Taiwan, dsb, saat ini adalah kelanjutan bhikkhuni dari Sri Lanka yang datang dan kemudian tinggal di China. 13 Dua orang yang berpendapat demikian di antaranya adalah M. Wipulasara Hamuduruwo dari Paramadhamma Cetya, Mount Lavinia, Sri Lanka dan Mr. S. Wijosundera, seorang Visiting Lecturer di Pali and Buddhist Institute, Singapore.
Banyak hal yang lucu dengan organisasi baru tersebut di Sri Lanka baru-baru ini. Sebenarnya, sesuai dengan Vinaya dalam tradisi Theravada, untuk menjadi Upjjhayini atau Pavattini (Uphajaya para Bhikkhuni), paling tidak dia harus menjadi Bhikkhuni paling sedikit dua belas tahun lamanya, 14 ; tetapi apa yang terjadi di Sri Lanka baru-baru ini? Sekitar satu tahun bahkan hanya beberapa bulan setalah "di-upasampada" di India, salah satu di antaranya langsung menjadi Upjjayini dan menyelenggarakan "upasampada" bagi para meeichi di Sri Lanka. Tidak hanya itu, mereka menyelenggarakan upacara "upasampada" tersebut hampir setiap tahun. Padahal menurut Vinaya Bhikkhuni, seorang Upjjayini tidak diperbolehkan melakukan upacara upasampada setiap tahun, tidak pula dia memberi upasampada lebih dari sekali dalam satu tahun. 15 Hal lucu lainnya, setelah mereka ditanya secara "bergurau" dari pihak sangha yang kontra dengan keberadaan mereka tentang siapkah mereka menerima Atthagarudhamma sesuai dengan Vinaya tradisi Theravada, mereka ternyata menolak dan keberatan dengan mengatakan bahwa Atthagarudhamma tersebut dibuat oleh para bhikkhu beberapa tahun setelah Sang Buddha, bukan oleh Sang Buddha. 16 Padahal secara historis, Atthagarudhamma tersebut dirumuskan oleh Sang Buddha sendiri agar ibu Pajapati dan lainnya mempertimbangkan niatnya terlebih dulu sebelum terjun menjadi bhikkhuni. 17 Mungkin masih banyak yang lucu lagi jika kita mau menyelidiki lebih lanjut tentang organisasi baru ini.
Bagaimanapun juga, masih banyak meeichi di Sri Lanka yang tidak mau "di-upasampada", dan tetap memilih hidup sebagai seorang meeichi tanpa embel-embel 'Theravada bhikkhuni', 18 Mbakyu Ani ataupun embel-embel lainnya. Mereka mempunyai alasan untuk tetap menjaga tradisi Theravada sebagaimana adanya, toh melaksanakan Sila dan Dhamma Sang Buddha tidak terbatas pada embel-embel yang ditempel di namanya. Sekedar embel-embel sebutan bhikkhu, samanera, bhikkhuni dsb, akan menjadi mubazir jika tingkah laku mereka secara konstitusi, pragmatik dan religious perspektif tidak sesuai. Yang penting adalah praktik, bukan embel-embel maupun sekedar teori. Justru sebenarnya betapa "berdosanya" menyalahgunakan, melecehkan dan menghianati tata tertib dan tata cara yang diakui keabsahannya secara historis maupun konvensional. Kita bisa juga mengambil inspirasi dari Kitab Ittivuttaka yang merupakan salah satu kitab dari Khuddhaka Nikaya yang juga merupakan "hasil kerja" seorang wanita biasa yang tanpa embel-embel apapun kecuali sebagai si pembantu Samavati selir raja Udena, bernama Khujjuttara. Dia dengan penuh keuletan mendengarkan kotbah Sang Buddha dan kemudian disampaikan pada wanita lainnya di istana raja. 19 Wanita tersebut karena motivasi dan dedikasi yang tulus dan iklas dalam mempraktikkan ajaran Sang Buddha, akhirnya mencapai kesucian tingkat pertama, Sotapana, meskipun dia hanya berembel-embel sebagai "babu" selir raja. 20
Yang menjadi tugas sekarang adalah memberi jawaban sesuai Dhamma Vinaya atas pertanyaan para intelektual yang berusaha untuk tetap berjalan sesuai dengan ajaran pra-sektarian agama Buddha. Benarkah diperlukan organisasi dengan nama Theravada Bhikkhuni yang secara konstitusional (Vinaya) sebenarnya sudah tidak memungkinkan lagi? Bukankah keberadaan organisasi baru tersebut mendeskritkan (kalau tidak bisa disebut melecehkan dan menghianati) tradisi Theravada, yang selama ini dikenal sebagai aliran agama Buddha (school of Buddhism) yang paling loyal dan penurut (faithful) terhadap Sang Buddha dan ajarannya? 21 Haruskah kita mengorbankan Vinaya yang selama ini merupakan darah nadi para bhikkhu dan para bhiksu yang bermoral hanya sekedar untuk membuat embel-embel yang sebenarnya sama sekali tidak diperlukan? Bukankah dengan terbentuknya organisasi baru tersebut merupakan suatu penghianatan dan pelecehan terhadap Vinaya yang selama ini telah dijaga oleh para bhikkhu ataupun bhiksu baik aliran Theravada maupun Mahayana agar kelangsungan ajaran Sang Buddha bisa dipertahankan?
Bagaimanapun toleransi dan saling menghormati memang tetap diperlukan. Tetapi tentunya adalah suatu hal yang janggal jika sekiranya seorang atau kelompok bhikkhu, atau bhiksu setelah mendapat upasampada secara sah dari tradisi tertentu, kemudian mendirikan tradisi baru yang berbeda dari Uphajaya dan Acariyanya. Secara tidak langsung, hal ini bisa disebut Sanghabeda (= memecah-belah sangha). Hal ini terjadi kalau kelompok bhikkhu atau bhiksu tersebut sebagai sangha karena berjumlah lebih dari empat atau lima bhikkhu. Jika setelah tiga kali dinasehati tetapi tetap melakukan pemisahan diri dari sangha tempat mereka bernaung, dan juga kemudian menganggap ajaran Sang Buddha, sebagai bukan ajaran Sang Buddha dan sebaliknya, Vinaya sebagai bukan Vinaya dan sebaliknya dsb. 22 Kalau hanya satu, dua orang atau tiga bhikkhu saja, maka usaha pemisahan diri tersebut disebut sangharaji. 23 Yang lebih serius lagi, seorang atau kelompok bhikkhu yang melakukan sanghabeda atau sangharaji seperti itu, menurut Vinaya tradisi Theravada, mereka melakukan pelanggaran sanghadisesa. 24 Selain itu, dalam kasus Bhikkhuni atau Bhiksunipun, baik itu aliran Theravada, Mahasanghika, Mahisasaka, Sarvastivada, Dharmagupta dan Mula-Sarvastivada menyebabkan terpecah-belahnya sangha seperti itu, terlepas hal ini disebut sanghabeda ataupun sangharaji, juga merupakan pelanggaran sanghadisesa, apabila Bhikkhuni atau Bhiksuni tersebut tidak mengubah sikap setelah dinasehati tiga kali dan tetap melakukan perpecahan dalam sangha. 25 Kalau sudah begitu, berwenangkah Sangha Theravada (di manapun berada) merestorasi atau campur tangan dengan seorang bhikkhuni atau bhiksuni yang telah melanggar Sanghadisesa yang secara yuridis, historis dan konstitusional berbeda seluk-beluk dan latar belakangnya, meskipun mereka mengembel-embel dirinya mengikuti tradisi Theravada? Kalau jawabannya ya, hal ini bisa diibaratkan dengan seorang siswa yang berbuat tidak senonoh di sekolah tempat ia belajar, sekolah lain yang sebenarnya tidak ada hubungan apapun dengan siswa tersebut, menghajarnya sampai pingsan agar siswa itu jera, atau seorang anak yang mencuri uang orangtuanya kemudian tetangga sebelah rumah yang sebenarnya tidak berhak menghukum anak tersebut, memukulnya sampai babak belur.
Akhirnya, seandainya organisasi baru itu pun mungkin diakui keberadaannya sebagai organisasi yang sah, karena selain orang-orangnya mendapatkan upacara pentahbisan sesuai dengan tata cara yang berlaku, dan diakui oleh masyarakat, tentunya dengan berat hati untuk diterima, kalau menamakan diri sebagai Bhikkhuni Sangha Theravada, walaupun mungkin secara praktik mereka mengikuti ajaran, vinaya dan tata cara tradisi Theravada. 26 Untuk disebut tradisi Theravada ataupun embel-embel lainnya, tentunya ada standar atau ukuran tertentu. Jika standar tertentu tersebut tidak terpenuhi, untuk apa harus menuntut untuk disebut dengan embel-embel "Theravada", nama yang sesuai adalah "Sangha Post-theravada Bhikkhuni" 27 atau "Simpatisan Bhikkhuni Sangha Theravada". Tetapi bagaimanapun, secara Vinaya Konstitusional, Sangha Theravada di manapun, tetap tidak mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sanghakamma, seperti ovada-akkhana 28 (para bhikkhuni meminta salah seorang dari sangha untuk memberi nasehat dalam hari uposatha), dan memberi upasampada bagi cikal bakal mereka.
Selain itu para "bhikkhuni Theravada baru" ini juga perlu mempertimbangkan bahwasanya yang mereka lakukan saat ini perpecahan dalam sangha (schism) atau tidak, karena secara historis mereka mendapatkan upasampada dari aliran tertentu -- non-Theravada, dan kemudian mereka menamakan diri Bhikkhuni Sangha Theravada dan mempraktikkan tradisi Theravada. Kalau yang sedang dilakukan adalah perpecahan dalam sangha (schism), dan mungkin ada dari pihak sangha (dalam hal ini sangha di mana mereka diupasampada) yang telah memberi nasehat sampai tiga kali, tetapi mereka tetap menuruti kemauan mereka sendiri, dan juga menganggap ajaran Sang Buddha, sebagai bukan ajaran Sang Buddha dan sebaliknya, Vinaya sebagai bukan Vinaya dan sebaliknya dsb. berarti mereka telah melakukan sanghadisesa. 29 Kalau mereka sudah melakukan pelanggaran sanghadisesa, yang mempunyai kewenangan untuk merestorasi mereka secara konstitusional adalah sangha di mana mereka mendapatkan upasampada. Selain itu, satu hal penting yang perlu diingat, setelah mereka direstorasi oleh sangha di mana mereka mendapatkan upasampada berkenaan dengan pelanggaran sanghadisesa tersebut, sesuai dengan tata-tertib (vinaya) yang ada, tentunya merekapun harus kembali mengikuti tradisi sangha di mana mereka diupasampada.
Hal penting lainnya, kalau keberadaan mereka dengan embel-embel yang baru, dan secara tidak langsung memecah diri dari sangha di mana mereka berasal, dan kemudian menganggap ajaran Sang Buddha, sebagai bukan ajaran Sang Buddha dan sebaliknya, Vinaya sebagai bukan Vinaya dan sebaliknya dsb. dan sangha tersebut mengetahui tentang hal itu tetapi tidak menasehati agar menghentikan pemecahan diri, berarti sangha tersebut tidak tahu tata tertib kebhikkhuan atau kebhiksuan (vinaya). Sangha atau kelompok para bhikkhu atau bhiksu yang tidak tahu atau tidak mentaati vinaya, tentunya mubazir untuk dijadikan lapangan untuk menanam jasa (puññakkhetta) 30 (baca: sebagai sumber inspirasi, tauladan, dan disokong oleh, bagi dan dari para umat awam). Jadi di sinilah ditemukan dilema yang sebenarnya tidak perlu ada. Oleh sebab itu, sebenarnya keberadaan organisasi baru tersebut akan lebih mendapat apresiasi kalau mereka tetap mempertahankan dedikasi, motivasi, posisi dan komitmen mereka secara historis maupun konstitusional, tanpa berkeinginan untuk mendapatkan embel-embel baru yang berarti pula tidak mengikuti norma-norma dan konvensional yang berlaku.
* (Penulis adalah seorang samanera di bawah naungan Sangha Theravada Indonesia yang saat ini adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan Specialist Buddhist Studies di Dept, Pali and Buddhist Studies, Faculty of Arts, University of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka.)
Catatan Kaki :
- Cullavagga Pali hal. 373-379.
- Satapatha Brahmana XIV : 1 :1:31.
- Shanaram Bhatchandra Deo, History of Jaina Monachism - From Inscription and Literature, Poona, 1956. p. 11.
- Cullavagga Pali hal 374-375. Delapan aturan penting tersebut misalnya 1. Seorang Bhikkhuni meskipun telah menerima upasampada satu abad lamanya harus tetap menghormat seorang bhikkhu meskipun baru satu hari mendapatkan upasampada. 2. Seorang Bhikkhuni harus tidak menyelesaikan masa vassanya di tempat di mana tidak ada bhikkhu tinggal, dst.
- idem hal. 373-379.
- Samantapasadika [91,10], Dipavamsa [8 vv. II, 12, Mahavamsa xix.65.
- idem.
- Catatan kaki pada artikel "Bhikkhuni" oleh H.R. Perera dalam encyclopedia of Buddhism Vol. III hal. 47.
- Keterangan lebih lanjut bisa hubungi Prof. C. Withanachchi, Dept. Pali and Buddhist Studies, University of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka.
- Cullavagga Pali hal. 391-395.
- idem.
- idem.
- Seandainya pernyataan inipun mungkin didukung dengan fakta historis, sebagai seorang yang konsistent dan loyal terhadap Vinaya yang dirumuskan oleh Sang Buddha, tentunya sangat sulit untuk menerima keabsahan keberadaan mereka sebagai Theravada bhikkhuni di millenium baru ini. Hal ini mengingat selain tradisi di tempat mereka mendapat upasampada telah "berevolusi" sekian lamanya dan telah membentuk tradisi lain yang jauh berbeda dari tradisi asal usulnya. Hal ini sebenarnya juga menimbulkan dilema dan penghianatan terhadap tata cara dan vinaya, baik dalam tradisi Theravada maupun Mahayana. Sebagai seorang Bhikkhu atau Bhiksu yang bermoral, hendaknya selalu ingat nasehat Sang Buddha bahwa Vinayo nama Buddhasasanassa ayu, vinaye thite sasanam thitam hoti (Sejauh praktik vinaya dan ajaran Sang Buddha dijaga, sejauh itu pula ajaran Beliau akan bertahan).
- Baca Dictionary of Early Buddhist Monastic Terms, oleh C.S. Upasak. Bharanti Prakhasan, India, 1975, hal 49.
- idem.
- Baca Catatan Kaki no. 9.
- Cullavagga Pali hal. 374-375.
- Baca catatan kaki no. 9.
- The Ittivuttaka the Buddha's Saying Translated from Pali by John D. Ireland, B.P.S. Kandy, Sri Lanka, hal 1.
- idem.
- Untuk lebih lanjut mengetahui tentang pendapat itu, hubungi Prof. P.D. Premasiri, Former Head Deparment Pali and Buddhist Studies, University of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka.
- Cullavagga Pali, hal. 305.
- idem.
- idem, C.S. Upasak, Dictionary of Early Buddhist Monastic Terms, Bharanti Prakhasan, Varanasi, India, 1975, hal. 210.
- The Bhikkhuni Patimokkha of the Six School, Translated into English by Chatsumarn Kabilsigh Ph.D., Thammasat University, Thailand 1991, hal. 11, 49, 87, 130, 171, 216.
- Mungkin dalam hal ini ada yang mengatakan yang penting adalah praktiknya, seperti yang saya telah katakan sebelumnya. Betul, saya setuju. Tetapi kalau memang betul-betul mengutamakan praktik, apa perlunya embel-embel baru? Tidak cukupkah titel, embel-embel, dan sebutan yang telah didapat sebelumnya untuk mempraktikkan ajaran Sang Buddha? Sudah pastikah dengan embel-embel yang baru didapat, apalagi dengan menghianati dan melecehkan peraturan (Vinaya) yang ada, mencapai tingkat-kesucian yang diharapkan? Selain itu, tidak mungkinkah meskipun sebagai umat awam, kalau dia memang berkemauan untuk mempraktikkan seluruh vinaya dan tata cara tradisi Theravada, tanpa menjadi seorang bhikkhu atau samanera?
- Dalam hal ini prefik "post" sama artinya dengan prefik "post" dalam kata "post-graduate" yang berarti setelah atau sesudah graduate, sebagai antonim suku kata "pra" seperti dalam kata "pra-sejarah" (sebelum sejarah), pra-sektarian (sebelumterbentuk sekte) dsb. Kembali ke atas
- Mahavagga Pali, hal. 117-121. Kembali ke atas
- Baca catatan kaki no. 24.
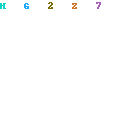
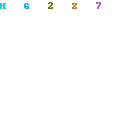
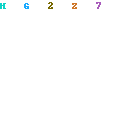
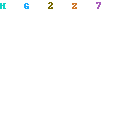
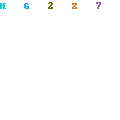
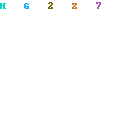
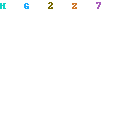
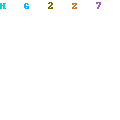
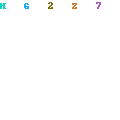




Tidak ada komentar:
Posting Komentar