| Nonsekte, Manifestasi Sikap Tunakeyakinan Dan Perangai Bunglonisme? |
| oleh: Jan Sanjivaputta |
Meskipun gerakan Nonsekte menjadi "hot topic" yang ramai diperbincangkan di kalangan umat Buddha, keterangan terinci tentang latar belakang dan asas pendiriannya, pola berpandangannya, tujuan utamanya, dan sikap serta perangai para pengikutnya masih tampak tersamar-samar dan ada kesan seolah-olah memang sengaja dirahasiakan oleh oknumnya karena beberapa alasan tertentu. Dengan berlandaskan pada pengertian bahwa "Alam tidak pernah mengajarkan kemunafikan kepada umat manusia untuk menyembunyikan suatu kenyataan. Betapapun pahit dan betapapun berat resikonya, kenyataan itu sesungguhnya bukanlah suatu hal yang teramat "tabu" untuk dibeberkan dengan jujur dan "bersahaja", semua keterangan tentang hal-hal di atas akan diungkap secara "blak-blakan" dalam artikel ini. Dengan begitu, segala sesuatu yang berada di balik gerakan yang sepintas tampak sebagai suatu usaha mulia itu tidak akan menjadi rahasia lagi, dan hanya akan tertinggal sebagai suatu kenangan belaka.
Di antara beberapa agama besar di dunia ini, barangkali agama Buddha merupakan salah satu —kalau bukan satu-satunya— agama yang memberikan porsi kebebasan untuk berpikir, dan berpandangan yang sangat besar bagi para penganutnya. Bahkan, corak kebebasan untuk berpikir, dan berpandangan ini mewarnai seluruh ajaran yang terkandung di dalamnya.
Corak kebebasan seperti itu tampaknya memang merupakan suatu hak yang amat didambakan serta dinanti-nantikan oleh sebagian besar umat manusia sehingga dengan sendirinya agama Buddha kerap diterima dengan sambutan yang luar biasa. Hal ini tentunya sangat menggembirakan. Namun, dibalik kegembiraan ini, terbersitlah sedikit keprihatinan setelah terbukti bahwa tidak sedikit di antara mereka sering menyalah-artikan kebebasan itu; yang membuat mereka terlena, dan bahkan lupa daratan sehingga mengumbar berbagai pikiran, dan pandangan pribadi yang liar, dan membuta. Padahal, corak kebebasan yang dipersembahkan oleh agama Buddha sebenarnya adalah suatu kebebasan berpikir, dan berpandangan yang terkendali, dan terarahkan —dalam artian tetap bertaatasas pada prinsip-prinsip kebenaran yang sahih (valid).
Lebih parah lagi, mereka selanjutnya saling mempertahankan pikiran, dan pandangan pribadinya yang liar, dan membuta itu dengan amat kukuh. Akibatnya, sebagaimana yang mudah diprakirakan, tersulutlah api perpilahan di antara mereka. Yang sedikit tragis, hal ini justru sudah mulai terjadi pada masa kehidupan Sang Buddha Gautama. Tampaknya, memang teramat mustahil jika di dunia ini ada satu pendiri agama —betapapun piawai kemampuan serta pengetahuan-Nya, dan betapapun adiluhur kharisma yang dimilikiNya— yang sanggup memandu, menuntun, dan membimbing "seluruh" umat manusia. Meski demikian, Sang Buddha Gautama dapat segera menanggulangi api perpilahan itu sehingga tidak sampai berkobar-kobar. Kebijaksanaan seorang Buddha memang merupakan pedoman utama bagi mereka untuk mengukur sampai seberapa jauh pola berpikir, dan berpandangan mereka telah menyimpang dari jalur yang telah terabsahkan, dan menjadi pengendali utama bagi mereka untuk segera kembali ke jalur itu.
Namun, tidak begitu lama setelah kemangkatan-Nya, api perpilahan tidak tertanggulangi lagi oleh generasi-generasi penerus-Nya hingga akhirnya menjurus kepada "penunasan" sekte-sekte yang mewadahi serta mewakili pikiran, dan pandangan pribadi sebagian dari mereka.
Sesungguhnya, terjadinya perpilahan dalam agama Buddha sepemangkat Sang Buddha Gautama masih boleh dinilai sebagai suatu kejadian yang tidak terlalu mencengangkan —menatap kenyataan bahwa memang tidak ada satu agama pun di dunia ini yang tetap tegar, dan sama sekali tidak mengalami perpilahan. Bahkan, jika diukur dari grafik jumlah sekte tunasannya, perpilahan yang terjadi dalam agama Buddha dapat dirasa tidak terlalu memprihatinkan.
Dengan bergulirnya sang kala, perkembangbiakan sekte yang berarti bertunasnya sekte-sekte baru tentunya juga ikut menanjakkan grafik jumlah. Rasanya, berhentinya penunasan sekte-sekte ini baru dapat sedikit diharapkan apabila kecenderungan untuk menahbiskan diri sebagai "nabi-nabi kecil" sudah benar-benar tercabut dari benak seluruh umatnya secara tuntas. Istilah "nabi-nabi kecil" ini sebenarnya bukanlah suatu ungkapan yang dicuatkan untuk mendeskreditkan semangat, dan upaya penunasan sekte-sekte baru, melainkan suatu ungkapan yang muncul secara alamiah sebagai suatu istilah yang hampir dapat melukiskan kecenderungan itu sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Banyak bukti yang bisa dirujuk untuk mempertanggungjawabkan pemunculan istilah ini. Pencantuman nama pribadi pendirinya sebagai nama sekte yang ditunaskan adalah salah satu bukti yang tak dapat dipungkiri. Seperti yang telah diketahui, sepanjang sejarah dunia ini, tidak ada seorang Buddha pun yang mengorbitkan nama pribadi-Nya menjadi nama agama yang didirikan; misalnya agama Gautama, agama Kasyapa, agama Sobhita, agama Padumuttara atau lain-lainnya. Pembandingan ini kiranya merupakan alasan yang cukup tepat untuk mempranyatakan bahwa hasrat untuk memburu popularitas sedikit atau banyak ikut ambil bagian dalam mencantumkan nama pribadi menjadi nama sekte itu. Tambahan pula, dalam hal-hal yang berpautan dengan kebenaran, bagaimanapun juga segi objektivitas kebenaran itu sendiri seharusnya yang lebih diutamakan alih-alih segi subjektivitas pembabar kebenaran.
Di tengah-tengah bergejolaknya kecenderungan untuk berkembang biak semacam itu, pada dewasa ini terseruak suatu kecenderungan yang bercorak lain. Kecenderungan yang bercorak lain ini lebih dikenal dengan sebutan gerakan "nonsekte" atau "tanmazhab". Di Indonesia, menurut beberapa narasumber yang dapat dipercayai, gerakan nonsekte ini memulai debutnya dua dasawarsa yang silam.
Gerakan nonsekte dengan gencar dipropagandakan sebagai suatu usaha yang disemangati dengan tujuan untuk menghambat penunasan sekte-sekte baru, dan sedapat mungkin diarahkan untuk mencampuradukkan, menyenyawakan serta menghablurkan kembali (recrystalization) ajaran seluruh sekte yang telah tertunas menjadi satu bentuk yang iras, Jadi, seseorang yang mengikuti gerakan nonsekte bukan berarti tidak menganut sekte apa pun, melainkan menganut semua sekte yang telah tertunas tanpa kecuali.
Pada galibnya, sejak awal penunasannya, setiap sekte memiliki suatu identitas masing-masing yang khas. namun, dengan diterimanya semua sekte; gerakan nonsekte, tak terelakkan lagi, berarti melumerkan identitas-identitas yang khas tersebut sehingga tidak ada satu identitas pun yang dapat disandang oleh gerakan nonsekte itu sendiri. Kalau dipaksakan untuk mengakui bahwa gerakan nonsekte itu mempunyai suatu identitas yang baru, maka satu-satunya identitas yang dapat disandangkan kepadanya hanyalah suatu identitas "campuran"; yang lahir melalui perkosaan secara brutal antar identitas yang secara khas dimiliki tiap-tiap sekte.
Jika dikaji secara seksama, terjadinya perpilahan dalam agama Buddha adalah suatu bukti nyata bahwa perbedaan "penafsiran" yang bergejolak di antara para penganutnya sudah tak mungkin dapat tetap dipertahankan dalam satu bentuk yang iras. Kalau memang masih mungkin dapat dipertahankan dalam satu bentuk yang iras, tentunya tidak akan terseruak sekte-sekte baru yang diorbitkan oleh beberapa orang tertentu —yang selanjutnya digelari sebagai pendiri sekte. Rasanya, para pendiri sekte ini lebih menyadari "ketakmungkinan" itu jika dibandingkan dengan para penganutnya pada masa sekarang ini karena, bagaimanapun juga, para pendiri tentunya jauh lebih piawai dalam memahami seluruh "seluk-beluk" penafsirannya sendiri atas ajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, kalau pada dewasa ini ada usaha yang ditujukan untuk mencoba mencampuradukkan, menyenyawakan serta menghablurkan kembali "penafsiran-penafsiran" itu dalam satu bentuk yang iras (nonsekte), maka dapatlah segera dipastikan bahwa usaha ini sangatlah jauh dari kenyataannya —kalau tidak boleh dikatakan sebagai suatu cita-cita yang terlalu muluk-muluk. Rupanya, di dunia yang hanya mau mengakui kewajaran, dan kenyataan ini masih ada juga orang yang melamunkan atau menghayalkan dirinya sebagai "pahlawan agung" dan siang bolong.
Sebagaimana yang terpampang dengan jelas, hingga saat ini gerakan nonsekte tidak berhasil mencapai tujuannya. Kegagalan ini rupanya bukanlah suatu kegagalan yang berakibat wajar. Tanpa bisa dielakkan, kegagalan ini beraklibat fatal, yaitu berputar-baliknya arah tujuan gerakan nonsekte, karena secara langsung maupun tak langsung; legal maupun illegal, gerakan nonsekte telah menunaskan satu "sekte baru" (sekte "nonsekte") —suatu kejadian yang pada mulanya ditentang dengan mati-matian. Sudah pasti bahwa "penunasan" sekte baru ini bagaimanapun juga hanyalah semakin memperkeruh masalah sekte.
Dalam menghadapi masalah sekte, umat Buddha di Indonesia sebenarnya dapat mengikuti teladan baik yang telah diperlihatkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menggariskan kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah agama. Lima agama besar secara resmi dan tak-sepihak telah diabsahkan eksistensinya, dan bagi setiap penduduknya, diberikan kebebasan penuh untuk menganut serta menjalankan ajaran "salah satu" dari kelima agama tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah sama sekali tidak pernah "menganjurkan" —apalagi "memaksa"— setiap penduduknya untuk menganut serta menjalankan ajaran "kelima" agama itu semuanya karena anjuran atau paksaan semacam ini hanya memberikan kesan merendahkan, dan bahkan mendaifkan agama-agama itu sendiri.
Juga, Pemerintah sama sekali tidak bermaksud menyinkretiskan kelima agama itu menjadi satu agama-tunggal. Penegasan ini dapat disimak melalui pernyataan mantan Menteri Agama, Prof. Dr. A. Mukti Ali, bahwa di Negara republik Indonesia, Sinkretisme yang hendak mencampuradukkan segala agama menjadi satu, dan menyatakan semua agama adalah sama —dengan dalih untuk merukunkan kehidupan beragama— jelas tak mungkin dapat diterima (Lihat: "Membina Kerukunan Hidup Antar umat Beriman", AP. Budiyono HD, halaman 231).
Memberikan ulasan tentang Sinkretisme —yaitu paham/pandangan hidup yang hendak menggabungkan unsur beraneka ajaran, ideologi, kepercayaan, dan agama, biarpun saling bertentangan— dalam kaitannya dengan toleransi, Umar Hasyim menuliskan bahwa:
"Memang ada sementara citra lain wajah toleransi yang menuju kepada pengaburan setiap agama yang akhirnya bahkan menuju kepada Sinkretisme. Hal ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh agama-agama tersebut. Citra yang salah dari wajah toleransi ini didengungkan demi kepentingan kerukunan beragama, tetapi akhirnya menuju kepada iklim yang tidak sehat".
Rinciannya yang pertama tentang citra salah yang menuju kepada Sinkretisme ialah pandangan bahwa semua agama adalah sama; sama benar, sama universal. Pandangan ini amat berbahaya karena akibatnya akan mencampuradukkan agama-agama, dan membuat orang hiprokrit terhadap agamanya sendiri, dan menghilangkan identitas agamanya. Yang kedua ialah usaha untuk memadukan/menyintesiskan semua agama sehingga membentuk agama baru (agama campuran) yang di dalamnya tercermin seluruh dasar dari semua agama tersebut; yang bisa dikatakan sebagai suatu aliran teosofi. Yang ketiga ialah suatu ajaran yang dasarnya adalah pemikiran untuk meninjau semua agama, diambil yang baik, yang sesuai dengan kembangan dunia modern sekarang ini, dan kemudian dijadikan suatu ikatan/jalinan baru, namun pemeluk agama masing-masing masih tetap dalam ikatan/jalinan agamanya semula.
Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, sangatlah jelas bahwa semangat gerakan nonsekte adalah suatu semangat yang bertentangan langsung dengan semangat luhur kebijaksanaan Pemerintah Indonesia yang berasaskan Pancasila. Patutlah disayangkan apabila hingga saat ini belum juga semua umat Buddha mau berusaha membangkitkan kesadarannya untuk menerapkan kebijaksanaan semacam yang telah diperlihatkan oleh Pemerintah Indonesia itu dalam kaitannya dengan masalah sekte.
Memang, siapa saja boleh sepakat dengan pernyataan bahwa "agama Buddha hanyalah satu". Namun, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu bahwa pernyataan ini sebenarnya lebih merujuk kepada kenyataan bahwa agama Buddha berhasil dalam menggalang dan membina "persatuan dan kesatuan dalam perbedaan" alih-alih mengacu kepada pengertian bahwa seluruh sekte dalam agama Buddha membawakan ajaran yang sama secara mutlak dan menyeluruh. Tak perlu disangkal bahwa topik-topik ajaran yang mencoraki semua sekte memang dapat dinilai nyaris sama. Namun, haruskah kesamaan suatu ajaran dinilai secara sederhana dengan didasarkan pada topik-topiknya saja? Bagi orang-orang yang berwawasan luas dan mendalam, penilaiannya rasanya tidak segampang itu. Kalau hanya topik-topik ajaran saja sudah cukup untuk dijadikan patokan dalam memperbandingkan suatu ajaran, barangkali tanpa bertutur panjang lebar dan dengan uraian yang argumentatif, seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa agama Buddha itu sama dengan agama Hindu, dan agama Kristen itu sama dengan agama Islam. Dalam ranah yang lebih luas, bisa pula dikatakan bahwa semua agama itu sama dan hanyalah satu! Namun, sesungguhnya, pernyataan ini jelas tidaklah benar dan tidaklah berdasar; yang secara tak langsung berarti mengatakan bahwa pemunculan suatu agama baru hanyalah seperti pembungkusan suatu "kebenaran yang sama" dengan bungkus lain —yang tentunya merupakan suatu hal yang mubazir, mengingat segi terpenting suatu agama (Dalam konteks ini: suatu sekte) adalah isinya; bukan bungkus atau kulitnya.
Sebenarnya, hal yang teramat penting untuk diperhatikan dalam memperbandingkan suatu ajaran itu bukanlah semata-mata topik-topik ajarannya, melainkan justru definisi, kupasan, dan jabaran topik-topik tersebut secara terinci. Hanya dengan memperhatikan hal yang teramat penting inilah, suatu pembandingan baru boleh dianggap cukup memadai dalam memberikan penilaian yang objektif tentang kesamaan atau perbedaan ajaran agama-agama, dan sekte-sekte.
Tak perlu dimungkiri bahwa sebagian besar sekte agama Buddha memang mewarisi "keturunan darah" ajaran-ajaran murni Sang Buddha Gautama. Namun, keturunan darah ini tidaklah seharusnya dijadikan data-tunggal untuk menghipotesis semua sekte sebagai sekte-sekte yang mutlak sama. Menghipotesis semua sekte sebagai sekte-sekte yang mutlak sama berdasarkan data-tunggal itu sesungguhnya tidaklah kurang kelirunya dengan menganggap seekor lutung dan seekor beruk sebagai hewan-hewan yang mutlak sama —kendatipun dipercayai berdasarkan data ilmiah bahwa keduanya berasal dari spesies sama yang berevolusi.
Memanglah benar bahwa ajaran Sang Buddha sama sekali tidak mengenal sekte. Ajaran Sang Buddha itu untuk semuanya. Namun, kenyataan ini kiranya tidaklah selalu berarti bahwa semua sekte "mau menerima" ajaran-ajaran murni Sang Buddha "menurut apa adanya". Karena itu, seseorang tidaklah seharusnya secara gegabah menganggap bahwa setiap ajaran suatu sekte tertentu pasti juga merupakan ajaran yang masih murni, atau tetap seperti pada awalnya. Hal yang sesungguhnya sangat penting inilah yang justru tidak ingin "dipersoalkan" oleh para pengikut gerakan nonsekte. Mereka seakan-akan berusaha menutup mata rapat-rapat atas hal ini. Agaknya, mereka sudah menangkap firasat bahwa melihat hal ini berarti juga melihat betapa rapuh landasan gerakan yang sedang diperjuangkan dengan menggebu-gebu itu, dan betapa rawan dampak negatif yang ditimbulkannya.
Tanpa mengingkari adanya kemiripan-kemiripan faktual, haruslah diakui secara jujur bahwa dalam ajaran setiap sekte terdapat perbedaan yang mendasar, dan bahkan pertentangan yang mencolok. Pula, perbedaan-perbedaan ini tidak semestinya disembunyikan atau disamar-samarkan dengan alasan dan dalih apapun juga. Malangnya, pembeberan perbedaan-perbedaan ajaran dalam sekte-sekte agama Buddha seringkali didakwa sebagai suatu hal yang sangat "tabu", dan yang tidak mencerminkan semangat toleransi (tenggang rasa). Budaya tak sehat semacam ini sebenarnya sudah tidak pada zamannya lagi untuk tetap dilestarikan secara primitif. Zaman sekarang adalah suatu masa yang di dalamnya keleluasaan, kejujuran dan keterbukaan dalam mengemukakan segala hal dipandang sebagai suatu tuntutan dan hak yang wajar, dan patut dilindungi serta dipenuhi terapannya. Sudah terlalu lama masyarakat Buddhis di Indonesia dibiarkan tergolek dalam suasana remang-remang seperti itu. Kini mereka sudah selayaknya diperlakukan secara dewasa dengan diberi kesempatan untuk melihat dengan jelas dan bebas segala kenyataan yang betapapun pahitnya, dan betapapun berat resikonya. pembeberan perbedaan-perbedaan faktual adalah data yang amat diperlukan oleh masyarakat Buddhis agar tidak sampai "keliru" dalam menilai serta memilih salah satu sekte agama Buddha. Dengan begitu, sejak dini mereka telah dapat mengetahui ke arah mana dirinya akan dipandu, dituntun, dan dibimbing melalui sekte yang dipilihnya, sehingga tidak akan merasa tersasarkan ketika sudah berada di awal, di pertengahan, atau bahkan di ujung perjalanan.
Sementara itu, penyekapan perbedaan-perbedaan ajaran sekte-sekte dalam suasana yang remang-remang secara langsung maupun tak langsung berarti memberikan kesempatan atau peluang kepada gerakan nonsekte untuk mengokohkan serta melebarkan sayapnya dengan lebih leluasa.
Di bawah ini akan dibeberkan tiga ajaran sekte-sekte yang berbeda. Tetapi, perlu diketahui sebelumnya bahwa pembeberan ketiga ajaran ini bukanlah berarti bahwa hanya sejumlah itu saja perbedaan-perbedaan yang bertebaran dalam sekte-sekte agama Buddha. Ketiga ajaran ini diharapkan dapat mewakili sekeranjang perbedaan yang bisa dikumpulkan, mengingat tidak mungkinnya membeberkan semuanya dalam artikel pendek ini.
Sekte Nichiren mempercayai (Entah berlandaskan pada sutra apa, —Penulis) bahwa tumbuh-tumbuhan dapat memperoleh Kesadaran Kebuddhaan apabila tumbuh-tumbuhan itu menguncarkan jampi-jampi Nammyohorengekyo —tanpa memerikan bagaimana cara penguncarannya (Lihat: "Sokagakkai", The Sekyo Press, Japan).
Sementara itu, hampir seluruh sekte lainnya menganggap bahwa tumbuh-tumbuhan tidaklah terklasifikasi sebagai "makhluk hidup" dalam arti yang sesungguhnya karena tumbuh-tumbuhan itu tidak memiliki "nâma" atau unsur-unsur batiniah, yakni kesadaran, pikiran, pencerapan, dan perasaan. Tumbuh-tumbuhan hanya memiliki satu bagian kehidupan, yaitu "rûpa" atau unsur-unsur jasmaniah, yakni unsur padat, cair, panas, dan gerak. Sekalipun demikian, sekte-sekte ini tetap mengakui bahwa tumbuh-tumbuhan itu mempunyai dorongan untuk hidup, memelihara kelangsungannya serta berkembang biak —sebagaimana yang telah dibuktikan oleh para ilmuwan. Namun, karena tidak memiliki unsur-unsur batiniah, tumbuh-tumbuhan tentunya tidak dapat dikatakan baik hati, jujur, disiplin, rendah hati, sopan santun, apalagi suci atau bahkan menjadi Buddha (memperoleh Kesadaran Kebuddhaan). Lebih jauh, sekte-sekte ini juga tidak mengakui metode penguncaran jampi-jampi Nammyohorengekyo —yang mencerminkan dorongan untuk mencari dan mendapatkan kemudahan-kemudahan belaka— sebagai ajaran murni Sang Buddha.
Sekte Bumi Murni/Pure Land (Sukhavati), bersendikan pada Sukhavati-Vyuha Sûtra (nas pendek), mempercayai adanya Buddha Amitabha yang atas dasar cinta kasih dan welas asih memberikan kesempatan bagi seluruh makhluk —kendatipun mereka telah melakukan berbagai durkarsa dan durtindak— untuk "memasuki" Bumi Murni ciptaannya asalkan mereka bersedia memenuhi satu syarat yang sangat sederhana dan mudah, yakni "merapalkan" nama dirinya (Buddha Amitabha) secara berulang-ulang. Bumi Murni yang dirujuk dalam sûtra itu adalah suatu "alam" di luar Triloka (Kâmaloka [Alam Hawa Nafsu], Rûpaloka [Alam Berbentuk], dan Ârûpaloka [Alam Nirbentuk]), yang secara berselirat dianggap bukan bersifat duniawi maupun bersifat mengatasi duniawi (adiduniawi). Makhluk-makhluk yang dilahirkan di Bumi Murni tersebut bukanlah lantaran pahala/jasa baik mereka masing-masing, melainkan semata-mata karena "bantuan" Buddha Amitabha sesuai dengan nadarnya yang ke-18 —bagi makhluk-makhluk yang merapal namanya.
Sementara itu, sebagian besar sekte lain yang bertaatasas pada sûtra-sûtra-awal Sang Buddha Gautama saja [tidak termasuk Sukhavati-Vyuha Sûtra], menganggap Buddha Amitabha sebagai "Tokoh Fiktif" yang keberadaannya tidak terbuktikan secara nyata —dalam artian bukan Buddha bersejarah (unhistorical Buddha). Pada segi lain, eksistensi Bumi Murni —baik sebagai alam di luar Triloka yang berbeda dengan Nirvana [menurut sekte Bumi Murni bentuk Indo-Sino], sebagai alam yang identik dengan Nirvana [menurut sekte Bumi Murni versi Jodo Shin Shu, Jepang] maupun sebagai alam yang bagaimanapun juga, secara tegas ditolak oleh sekte-sekte lain tersebut. Bagi sekte-sekte lain tersebut, Sukhavati-Vyuha Sûtra —baik yang bernas pendek maupun yang bernas panjang— dan juga Amitayurdhyana Sûtra [sûtra lain yang dipercayai dan dijadikan landasan oleh sekte Bumi Murni], dinilai tidak lebih sebagai dongeng-dongeng yang mencatutkan nama Sang Buddha Gautama sebagai penutur/pembabar sûtra-sûtra itu. Mengenai kelahiran di Bumi Murni yang bebas dari penderitaan, yang didapat bukan karena jasa baik sendiri melainkan semata "lantaran" bantuan Buddha Amitabha, sekte-sekte lain tersebut berulas bahwa cara itu jelas merupakan pengingkaran mutlak terhadap Dalil Karma [salah satu ajaran utama Buddha bersejarah] yang memerikan bahwa setiap makhluk memiliki, mewarisi, terlahir, berhubungan, dan terlindung oleh karmanya masing-masing —sekalipun "rapalan" itu dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang "cukup baik". "Kalau hanya melalui rapalan yang sangat sederhana dan mudah tersebut, seluruh makhluk dapat terbebaskan dari penderitaan, Sang Buddha Gautama tentunya tidak perlu bersusah payah membabarkan ajaran-ajaran lain yang sekarang ini termaktub dalam Tiga Himpunan Kitab!", tegas para penganut sekte-sekte lain tersebut dengan argumentetif.
Sekte-sekte yang bertumpukan pada Saddharma Pundarika Sûtra mempercayai bahwa kebebasan dari cengkeraman penderitaan dapat diraih apabila suatu makhluk telah mencapai Pencerahan Agung sebagai Samyaksambuddha saja. Inilah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lainnya lagi! Suatu makhluk yang telah mencapai Pencerahan Agung sebagai Arhat tidak diakui telah mencapai Tujuan Akhir —dalam artian telah terbebas dari cengkeraman penderitaan, dan meraih Nirvana. Bahkan, kedudukan Arhat diletakkan di bawah Bodhisattva atau calon Buddha [suatu makhluk yang baru bercita-cita/berusaha untuk mencapai Pencerahan Agung sebagai Samyaksambuddha]. Lebih jauh, Arhat dikatakan masih dapat bertumimbal lahir lagi di Alam Semesta yang terliputi oleh penderitaan ini.
Sementara itu, sekte-sekte lain yang tidak mempercayai Saddharma Pundarika Sûtra sebagai sabda murni Sang Buddha Gautama, berkeyakinan bahwa untuk mencapai kebebasan dari cengkeraman penderitaan, suatu makhluk dapat menempuhnya dengan jalan menjadi Samyaksambuddha, Pratyekabuddha, ataupun Arhat. Pencerahan Agung yang dicapai melalui ketiga jalan ini tidaklah berbeda sama sekali. Tidak ada sistem hirarki atau diskriminasi yang berlaku bagi suatu makhluk yang telah meraih Nirvana. Tujuan Akhir melalui "salah satu" dari tiga jalan itu. Setelah pencapaian ini, ia sudah tidak akan bertumimbal lahir di alam mana pun juga, sehingga dengan sendirinya berarti telah terbebas dari cengkeraman penderitaan dalam bentuk atau wujud apa pun juga. Nuansa di antara ketiga jalan itu hanya terletak pada cita-cita luhur yang dikembangkan. Oleh karena itu, setiap makhluk boleh, dan dapat memilih "salah satu" dari ketiga jalan itu sesuai dengan kehendaknya. Apabila salah satu dari tiga jalan itu sudah berhasil ditempuh, ia tidak perlu berhasrat —dan memang tidak mungkin dapat— menempuh dua jalan lainnya. Jadi, ketiganya bukanlah suatu tahapan yang harus ditempuh secara beruntun melainkan suatu alternatif manasuka. Tidak ada keharusan atau bahkan paksaan untuk menjadi Samyaksambuddha karena Kesamyaksambuddhaan bukanlah satu-satunya jalan atau jalan tunggal (Ekayâna/Buddhayâna).
Dalam artikel pendek ini, sama sekali tidak ada usaha untuk mencoba "mengadili" ketiga ajaran sekte-sekte tersebut di atas karena usaha ini tentunya akan menimbulkan kesan subjektif. Ketiga ajaran sekte tersebut dibeberkan semata-mata hanyalah untuk membuktikan bahwa memang benar-benar ada sebagian ajaran sekte-sekte yang berbeda. Pembuktian ini berarti menggugurkan anggapan sementara orang —terutama para pengikut gerakan nonsekte— bahwa perbedaan-perbedaan dalam ajaran sekte-sekte agama Buddha itu sekedar asap yang ditiupkan ke ruangan tak berapi.
Sepertinya terlalu munafik jika ajaran sekte-sekte tersebut dianggap tidak mengandung perbedaan. Juga, rasanya tidak ada satu alasan yang tepat untuk menganggap bahwa perbedaan-perbedaan itu tidaklah begitu mendasar. Seandainya dalih ini dikilahkan, hal ini jelas tak ubahnya dengan mengatakan bahwa agama Buddha sama sekali tidak mempunyai ajaran dasar (fundamental teaching).
Apabila di antara sekte-sekte yang "sedarah-langsung" saja terdapat ajaran-ajaran yang kontradiktif seperti itu, agaknya dapat dipastikan bahwa tidak akan dijumpai kesulitan sedikit pun untuk mencari dan menemukan ajaran-ajaran yang lebih kontradiktif dalam sekte-sekte yang "tak-sedarah-langsung" —dalam artian sekte-sekte yang merupakan hasil campuran antara suatu sekte agama Buddha tertentu dengan suatu "agama" atau "kepercayaan" yang sangat berlainan, baik pembawa ajaran maupun kitab sucinya.
Karena terbukti adanya ajaran-ajaran yang kontradiktif, maka sudah tentu bahwa seseorang baru dapat menanamkan keyakinan pada ajaran [tertentu] sekte yang satu dengan mencabut terlebih dahulu keyakinan pada ajaran [tertentu] sekte yang lainnya. Singkatnya, keyakinan pada ajaran [tertentu] sekte-sekte itu tidaklah mungkin dapat ditanamkan secara bersama-sama. Meski demikian, ajaran [tertentu] sekte-sekte itu memang secara mentah-mentah dapat "diakui" semuanya. Namun, jika hal itu telah dilakukan, seseorang niscaya akan kehilangan kemampuan dan kesempatan untuk menanamkan keyakinan apa pun juga. Selanjutnya, ia secara tragis berarti telah menjadi orang yang "tunakeyakinan" (faithless). Jadi, para pengikut gerakan nonsekte —yang mengakui ajaran semua sekte [betapapun kontradiktif ajaran-ajaran ini]— tak syak lagi, semuanya adalah orang-orang yang tunakeyakinan.
Sesungguhnya, tanpa mengurangi penghargaan dan penghormatan terhadap sekte-sekte lain, seseorang dapat, dan boleh menganggap bahwa sekte yang dipilih dan dianutnya adalah sekte yang paling benar dan paling murni sejauh ia telah mempelajari serta menelaah ajaran sekte-sekte lain tanpa diliputi sikap apriori yang tak beralasan tetapi benar-benar berdasarkan pada objektivitas. Dari penelaahan yang objektif inilah seseorang akan dapat melihat kenyataan bahwa perbedaan ajaran sekte-sekte sebenarnya tidaklah hanya berkisar pada segi penyajian ataupun pendekatan (approach)-nya tetapi bahkan lebih jauh dan lebih lebar daripada ini —suatu kenyataan yang sangat bertolak-belakang dengan apa yang ditulis oleh Harsa Swabodhi dalam buku "Buddha Dharma Pelbagai Yana".
Menganggap semua sekte sama benarnya dan sama murninya adalah langkah awal yang menggiring dan menjerumuskan seseorang dalam gerakan nonsekte. Setidak-tidaknya, sikap ini akan mempermudah seseorang berpindah-pindah sekte. Orang yang seperti ini kiranya dapat dipersamakan dengan sebuah kapal yang tak berkemudi. Di karang mana pun kapal itu terdampar, semua itu dianggap sebagai dermaga-dermaga tujuannya yang tak-jelas dan tak-pasti. Pada taraf yang lebih rendah, sikap ini akan menimbulkan "kehausan" tak-wajar untuk selalu mengais-ngais, dan me-"leles"-i ajaran sekte-sekte lain, yang mencerminkan ketak-mantapan keyakinan seseorang bahwa ajaran yang mirip sebetulnya juga terdapat dalam sektenya sendiri tetapi tidak pernah dicoba digali dengan tekun. Sebaliknya, seseorang yang memiliki keyakinan yang mantap, tunggal, dan utuh terhadap sektenya tentu tidak akan berkhianat dengan "menomor-duakan" atau "menomor-gandakan" sektenya.
Bagi para pengikut gerakan nonsekte, keyakinan yang mantap, tunggal, dan utuh adalah suatu bentuk keyakinan yang amat "ekstrem" dan "kontroversial". Namun, sesungguhnya, kenyataannya tidaklah demikian. Bahkan, justru keyakinan seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang tidak ingin dirinya diibaratkan seperti "pucuk batang bambu". Perlu dipahami bahwa keyakinan seperti ini bukanlah dijiwai dengan duritikad untuk memilah-milah sekte-sekte agama Buddha, dan kemudian menjebloskannya dalam kotak-kotak yang berbeda, melainkan semata-mata untuk menempatkan sekte-sekte tersebut pada proporsi yang sebenarnya. Juga, keyakinan yang mantap, tunggal, dan utuh tidaklah mengurangi arti dan semangat toleransi.
Kelayakan bertoleransi yang dapat dan telah digalang dan dibina oleh para penganut suatu sekte terhadap sekte-sekte lain tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip yang berlaku dan segi-segi kewajaran, sebenarnya tidaklah sesempit yang diperkirakan oleh para pengikut gerakan nonsekte —yang menggembar-gemborkan toleransi mutlak yang membuta.
Toleransi yang sesungguhnya bukanlah suatu sikap yang baru dapat dibentuk dengan terlebih dahulu menanggalkan ajaran sekte masing-masing, dan kemudian mencampur-adukkan, menyenyawakan serta menghablurkannya menjadi satu bentuk yang iras.
Juga, toleransi yang sesungguhnya bukanlah berarti secara munafik membenarkan ajaran sekte-sekte lain yang terbukti tidak selaras [Baca: bertentangan] dengan sekte sendiri, melainkan "memberikan hak dan kebebasan" kepada para penganut sekte-sekte itu untuk mempercayainya.
Selain itu, toleransi yang sesungguhnya juga bukanlah berarti harus "menyumbat" pembabaran dan penyebaran ajaran sekte sendiri semata-mata karena ajaran ini bertentangan dengan ajaran sekte-sekte lain. Kalau penyumbatan semacam ini dikualifikasikan sebagai wujud toleransi, maka di dunia ini sesungguhnya tidak ada satu pendiri agama atau pendiri sekte pun (apalagi penganutnya) yang pernah bertoleransi. Betapa tidak. Semua agama atau sekte lahir di tempat yang masyarakatnya telah menganut —secara aktif maupun pasif— agama atau sekte lain yang jelas berbeda. Contohnya, agama Buddha lahir di India pada masa agama Brahmaisme telah mendarah daging pada masyarakat di sana sehingga atmosfirnya betul-betul hanya disarati oleh sistem filsafat dan kebudayaan Brahmaisme. Jika Sang Buddha Gautama dipaksakan untuk menjalankan "toleransi" dengan menyumbat pembabaran dan penyebaran ajaran-Nya —yang jelas berbeda dengan sistem filsafat dan kebudayaan Brahmaisme— maka tak syah lagi, agama Buddha pasti tidak akan pernah muncul di dunia ini!
Dalam pada itu, keyakinan yang mantap, tunggal, dan utuh haruslah dibedakan dari "fanatisme bersekte" karena fanatisme bersekte adalah suatu kepercayaan yang membuta kepada sektenya sendiri tanpa pengertian yang benar, dan obyektif; yang kadang-kadang berkelanjutan menjadi semacam dorongan untuk "memaksa" orang lain mengikuti dan memasuki sektenya sendiri —suatu tindakan yang jelas bertolak-belakang dengan ajaran murni Sang Buddha Gautama yang penuh tenggang rasa, dan pengertian yang arif.
Keyakinan yang mantap, tunggal, dan utuh adalah suatu keyakinan yang tidak mengenal istilah "membagi-bagi rasa percaya" dengan porsi yang sama kepada semua sekte. Membagi rasa percaya dengan porsi yang sama kepada semua sekte jelas merupakan suatu bentuk kepercayaan berselirat yang membingungkan. Sangatlah sukar untuk melukiskan betapa rancu dan betapa awut-awutan pola berpikir dan berpandangan orang-orang yang terjangkiti oleh wabah kepercayaan berselirat ini. Bisa dikatakan bahwa pola berpikir dan berpandangan orang yang tidak memasuki satu sekte pun —dalam artian tidak menganut agama apa pun— sesungguhnya masih kelihatan lebih "rapi" daripada orang-orang yang kepercayaannya berselirat. Betapa tidak! Misalnya, seandainya dipertanyakan kepada orang yang tergolong belakangan ini, apakah Arhat itu masih bertumimbal lahir lagi, maka akan diperoleh jawaban yang membenarkan, tetapi tidak begitu lama kemudian ia menukar jawaban itu dengan jawaban yang menyalahkan, dan beberapa saat lagi ia menyodorkan kedua jawaban itu bersama-sama atau mungkin malah mencabut keduanya. Andaikata boleh diibaratkan dengan contoh yang gamblang [kalau tak boleh, anggap saja wacana berikut ini tidak tertera —Penulis], orang yang tergolong belakangan itu perangainya tak ubahnya seperti seekor binglon yang selalu berganti-ganti warna kulit atau/dan bersemburkan aneka warna kulit; tetapi ia sendiri sesunguhnya tidak mempunyai warna kulit yang khas. Perangai bunglonisme semacam ini, tak meragukan lagi, adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan nonsekte.
Beberapa pemimpin gerakan nonsekte merasa bangga bahwa di tempat ibadahnya, dapat diperoleh ajaran dari semua sekte, tidak berkecuali. Tanpa disadari, kebanggan ini sebenarnya justru menurunkan status tempat ibadah sebagai tempat suci ke tempat yang tidak lebih tinggi dari sebuah tempat semacam pasar swalayan (super market) di mana segala barang dari "pelbagai produk" diperdagangkan semata-mata hanya untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari para pelanggannya yang bermacam-macam keperluannya. Di sini jelas terlihat adanya pergeseran prinsip-prinsip keagamaan —bagian terpenting suatu tempat ibadah— oleh prinsip-prinsip perdagangan yang sekadar menuruti dan mengikuti "selera" semua orang yang latar belakangnya beraneka ragam.
Pada segi lain, perangai bunglonisme juga dapat didiagnosis dari pergantian aneka model jubah bhiksu —yang sebetulnya merupakan ciri khas tiap-tiap sekte yang mempunyai masyarakat kebiaraan— tanpa melalui prosedur penahbisan ulang (yati) yang resmi. Bagi mereka yang ikut menghadiri Peringatan Waisak Nasional 2530 di Candi Mendut baru-baru ini, diagnosis ini akan dapat terbuktikan karena di sela-sela rangkaian acara itu terdapat seorang bhiksu yang "kober" "membunglonkan diri" seperti itu. Sesungguhnya, terselenggarakannya Peringatan Waisak Nasional sudah merupakan bukti nyata bahwa para penganut pelbagai sekte telah berhasil menggalang serta membina persatuan dan rasa kebersamaan yang erat dan harmonis. Entah mengapa ada saja oknum tertentu yang mencemarkan persatuan serta rasa kebersamaan itu dengan [secara langsung maupun tak langsung] menohok perasaan para penganut sekte yang model jubah bhikkhunya "dibajak" secara terang-terangan seperti itu —kendatipun memang ada hak dan kebebasan untuk melakukannya, mengingat masih belum adanya "copy-right" dalam bidang ini.
Dari seluruh telaahan dalam artikel ini, agaknya tidak ada satu simpulan akhir yang dapat ditarik selain menyatakan bahwa gerakan nonsekte memang benar-benar merupakan manifestasi sikap tunakeyakinan dan perangai bunglonisme. Bagaimanapun juga, sikap tunakeyakinan dan perangai bunglonisme yang merupakan wabah batiniah yang paling berbahaya ini jelas perlu segera ditanggulangi secara tuntas. Penanggulangannya tentunya menjadi kewajiban bagi setiap orang yang mengaku beragama Buddha, dan ingin tetap melestarikan agama yang dianutnya itu sendiri. Kegagalan ataupun keberhasilan penanggulangan ini sangat ditentukan oleh kadar "loyalitas" (kesetiaan) mereka terhadap ajaran-ajaran murni Sang Buddha Gautama. Apabila pertanyaan yang bernada seperti, "Siapkah mereka membuktikan loyalitas ini?", mendapatkan jawaban positif yang serempak, hal ini kiranya merupakan isyarat langsung bagi gerakan nonsekte untuk segera menyiapkan batu nisan sebagai markah tamat kelangsungannya....!***
Sudah merupakan suatu kecenderungan umat manusia untuk gampang terbujuk dan terpikat oleh ide atau gagasan yang disajikan secara muluk-muluk, yang dalam kenyataannya hanya berupa impian kosong melompong.
| Sumber: |
| Untaian Dhammakatha (Kumpulan Tulisan), Jan Sanjivaputta, Yayasan Pancaran Dharma, Jakarta, 1987. |
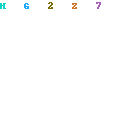
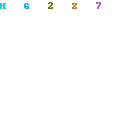
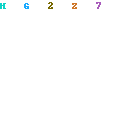
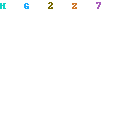
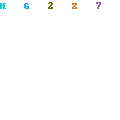
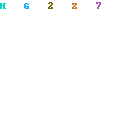
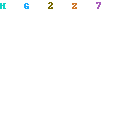
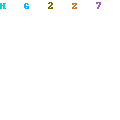
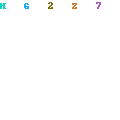




Tidak ada komentar:
Posting Komentar