Sabtu, 16 April 2011
EMPAT KESUNYATAAN MULIA; Kesunyataan Mulia ke tiga: Dukkha Nirodha (3)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Buddha Gautama

Labels
- Abhidhamma (3)
- Ajahn Brahm (1)
- Ajahn Brahm - Wisdom of Silence (7)
- Anthony de Mello SJ - Berbasa-basi Sejenak (5)
- Anthony de Mello SJ - Burung Berkicau (9)
- Anthony de Mello SJ - Doa Sang Katak (16)
- artikel buddhist (48)
- Berkah (1)
- Bhikkhu Girirakkhito Mahathera (1)
- Bhikkhu Jotidhammo Mahathera (4)
- Bhikkhu Khantipalo (1)
- Bhikkhu Sri Paññavaro Mahathera (4)
- Bhikkhu Subalaratano (3)
- Bhikkhuni (1)
- Buddha dan Sains (11)
- Buddhadasa Bhikkhu - THE TRUE NATURE OF THINGS (2)
- Buddhavamsa (1)
- catatan ajahn chah (4)
- catatan dhamma (4)
- Cinta Kasih (1)
- dhammachakka (52)
- Dhammadesana (39)
- Dhammapada (2)
- Digha Nikaya (1)
- Download (1)
- Dr. K. Sri Dhammananda (5)
- EMPAT KESUNYATAAN MULIA (4)
- Font Pali (1)
- H.H Somdet Phra Nyanasamvara (3)
- Hidup Lebih Baik (1)
- HTML Help Doc (1)
- Identitas Umat Buddhis (1)
- INTISARI AGAMA BUDDHA (3)
- Itivuttaka (1)
- Jan Sanjiva (1)
- Jataka (4)
- Magha Puja (1)
- meditasi (7)
- Milinda Panha (19)
- Must have (1)
- Parita Suci (3)
- Petavatthu (1)
- Pindapatta (1)
- Puja Bhakti (2)
- RAPB (1)
- Riwayat Agung Para Buddha (1)
- Riwayat Singkat Guru Agung Buddha Sakyamuni (13)
- samaggi-phala.or.id (48)
- serba-serbi (7)
- serba-serbi galaksi (6)
- Sila (1)
- Spelling (1)
- sutta pitaka - Anguttara Nikaya (1)
- sutta pitaka - Khuddaka-Nikaya (17)
- sutta pitaka - Digha Nikaya (1)
- sutta pitaka - Samyutta Nikaya (2)
- sutta pitaka - Majjhima Nikaya (1)
- Suttanipata (1)
- Tanya Jawab (5)
- teori ajaran sang buddha (5)
- Tipitaka (1)
- TIPITAKA - kitab suci agama buddha (6)
- Tokoh (1)
- Udana (1)
- Ulasan Dhamma (34)
- Ven Narada Mahathera (11)
- Ven. Buddhadasa Bhikkhu (3)
- Ven. S. Dhammika (1)
- Vinaya Pitaka - Suttavibhanga (1)
- www.samaggi-phala.or.id (37)
- Y. M. Mahāsi Sayādaw (1)
- Y.A. Khantipalo (1)
- Y.M. Bhikkhu Girirakkhito Mahathera (6)
Blog Archive
-
▼
2011
(366)
-
▼
April
(289)
- Mittamitta-Jataka
- Kaka Jataka
- KETUHANAN YANG MAHAESA DALAM AGAMA BUDDHA
- DASAR-DASAR MEDITASI VIPASSANĀ
- Berbasa-basi Sejenak
- Berbasa-basi Sejenak
- Berbasa-basi Sejenak
- Berbasa-basi Sejenak
- Berbasa-basi Sejenak
- Burung Berkicau
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Doa Sang Katak
- Burung Berkicau
- Burung Berkicau
- Burung Berkicau
- Burung Berkicau
- Burung Berkicau
- Burung Berkicau
- Burung Berkicau
- Burung Berkicau
- TIPITAKA - kitab suci agama buddha (silahkan klik ...
- Suttavibhanga
- Khuddaka-Nikaya (silahkan klik judul kitab yang i...
- Anguttara Nikaya (silahkan klik judul kitab yang i...
- Samyutta Nikaya (silahkan klik judul kitab yang in...
- Majjhima Nikaya (silahkan klik judul kitab yang in...
- Digha Nikaya (silahkan klik judul kitab yang ingin...
- 14. DHAMMIKA SUTTA : Ringkasan kehidupan bhikkhu d...
- 13. SAMMAPARIBBAJANIYA SUTTA : Kehidupan Tak-berum...
- 12. VANGISA SUTTA : Vangisa mendapat kepastian bah...
- 11. RAHULA SUTTA : Sang Buddha merekomendasikan ke...
- 10. UTTHANA SUTTA : Desakan yang kuat untuk menger...
- 9. KIMSILA SUTTA : Perilaku yang Benar
- 8. NAVA SUTTA : Bagaimana memilih guru yang baik d...
- 7. BRAHMANADHAMMIKA SUTTA : Perilaku yang Baik bag...
- 6. DHAMMACARIYA SUTTA : Kehidupan yang Baik
- 5. SUCILOMA SUTTA : Khotbah yang serupa dengan Ala...
- 4. MAHAMANGALA SUTTA : Perbuatan yang Menjamin Keb...
- 3. HIRI SUTTA : Mengenai persahabatan sejati
- 2. AMAGANDHA SUTTA : Arti spiritual dari ‘ketidakm...
- 1. RATANA SUTTA : Puji pujian terhadap ‘permata-pe...
- 12. DVAYATANUPASSANA SUTTA : Asal Mula dan Penghen...
- 11. NALAKA SUTTA : Kelahiran Buddha yang akan data...
- 10. KOKALIKA SUTTA : Akibat mengerikan dari ucapan...
- 9. VASETTHA SUTTA : Definisi yang Benar tentang ‘B...
- 8. SALLA SUTTA : Anak Panah - Perenungan tentang k...
- 7. SELA SUTTA : Sang Buddha meyakinkan Sela dan te...
- 6. SABHIYA SUTTA : Seorang pertapa yang berkelana ...
- 5. MAGHA SUTTA : Magha
- 4. PURALASA SUTTA : Kue Kurban - Kepada siapa pers...
- 3. SUBHASITA SUTTA : Kata-kata yang Baik
- 2. PADHANA SUTTA : Perjuangan Sang Buddha Melawan ...
- 1. PABBAJJA SUTTA : Meninggalkan Keduniawian (Tent...
- CERITA-CERITA ISTANA ALAM DEWA (VIMANAVATTHU)
- 16. SARIPUTTA SUTTA : Praktek latihan seorang bhikkhu
- 15. ATTADANDA SUTTA : Perilaku Kekerasan
- 14. TUVATAKA SUTTA : Jalan Menuju Kebahagiaan
- 13. MAHAVIYUHA SUTTA : Penyebab-penyebab Utama Per...
- 12. CULAVIYUHA SUTTA : Penyebab-penyebab Kecil Per...
- 11. KALAHAVIVADA SUTTA : Perselisihan dan Pendirian
- 10. PURABHEDA SUTTA : Kelakuan dan ciri-ciri seora...
- 9. MAGANDIYA SUTTA : Magandiya
- 8. PASURA SUTTA : Perselisihan Mempertahankan Pand...
- 7. TISSAMETTEYYA SUTTA : Sang Buddha menjelaskan j...
- 6. JARA SUTTA : Kelapukan
- 5. PARAMATTHAKA SUTTA : Kesempurnaan
- 4. SUDDHATTHAKA SUTTA : Kemurnian
- 3. DUTTHATTHAKA SUTTA
- 2. GUHATTAKA SUTTA : hindari kemelekatan untuk men...
- 1. KAMA SUTTA ; Kenikmatan indera yang harus dihin...
- Asal Mula Agama Buddha di Indonesia
- Kejadian Bumi dan Manusia dalam Pandangan Buddhis
- Tiga Karateristik Kehidupan
- arti kamma? - ajahn brahm
- Apa makna dari Sila? - ajahn brahm
- Apa yang kita maksudkan dengan NIBBANA? - ajahn brahm
- Apa yang kita maksudkan dengan SURGA? - ajahn brahm
- Kisah Perbuatan Lampau Sang Buddha
- Kisah Kembalinya Sang Buddha
- Kisah “Kata-kata Kebahagiaan Sang Buddha”
- 7 Keunggulan Ajaran Buddha
- Pertanyaan & Jawaban Ajahn Chah (terjemahan google)
- PERSEMBAHAN (PUJA) - Terjemahan buku Wisdom of Sil...
- LIMA RINTANGAN (NIVARANA) - Terjemahan buku Wisdom...
- SATIPATTHANA – EMPAT PERHATIAN KESADARAN - Terjema...
- Ketika Badan Jasmani Menghilang - Terjemahan buku ...
-
▼
April
(289)
Entri Populer
-
40 OBJEK SAMATHA MEDITASI. oleh Panna Nanda Bhikkhu pada 03 April 2011 jam 21:47 Samatha Bhavana 1. EMPAT PULUH MACAM OBYEK MEDITASI ...
-
Vipassana Bhavana 1. EMPAT MACAM SATIPATTHANA Dalam melaksanakan Vipassana Bhavana, obyeknya adalah nama dan rupa (batin dan materi),...
-
(Berdasarkan buku Paritta Suci terbitan Sangha Theravada Indonesia) 1. PEMBUKAAN Pemimpin puja bakti : ...
-
Manfaat Melatih Kesabaran Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Manfaat Melatih Kesabaran Khantῑ paramaṁ tapo tῑtikkhā Mela...
-
oleh: Bhikkhu Subalaratano Namo tassa bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato Sammasambud...
-
oleh: P. Sabar Hingga saat ini masih juga terdapat kesalahpengertian di antara umat Buddha mengenai siapakah yang disebut S...
-
Misteri Panglima Burung Panglima Perang Orang Dayak Hai bro beberapa hari ini kita diramaikan berita tentang kematian orang yang pal...
-
Tipitaka Kanon Pali atau Tipitaka berarti tiga keranjang penyimpanan Kanon (Kitab Suci). Selama beberapa abad sabda-sabda Sang...
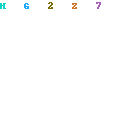
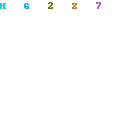
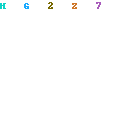
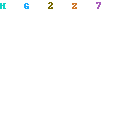
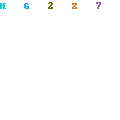
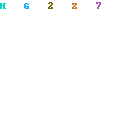
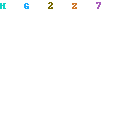
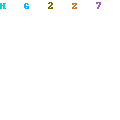
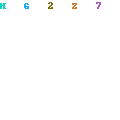



Tidak ada komentar:
Posting Komentar